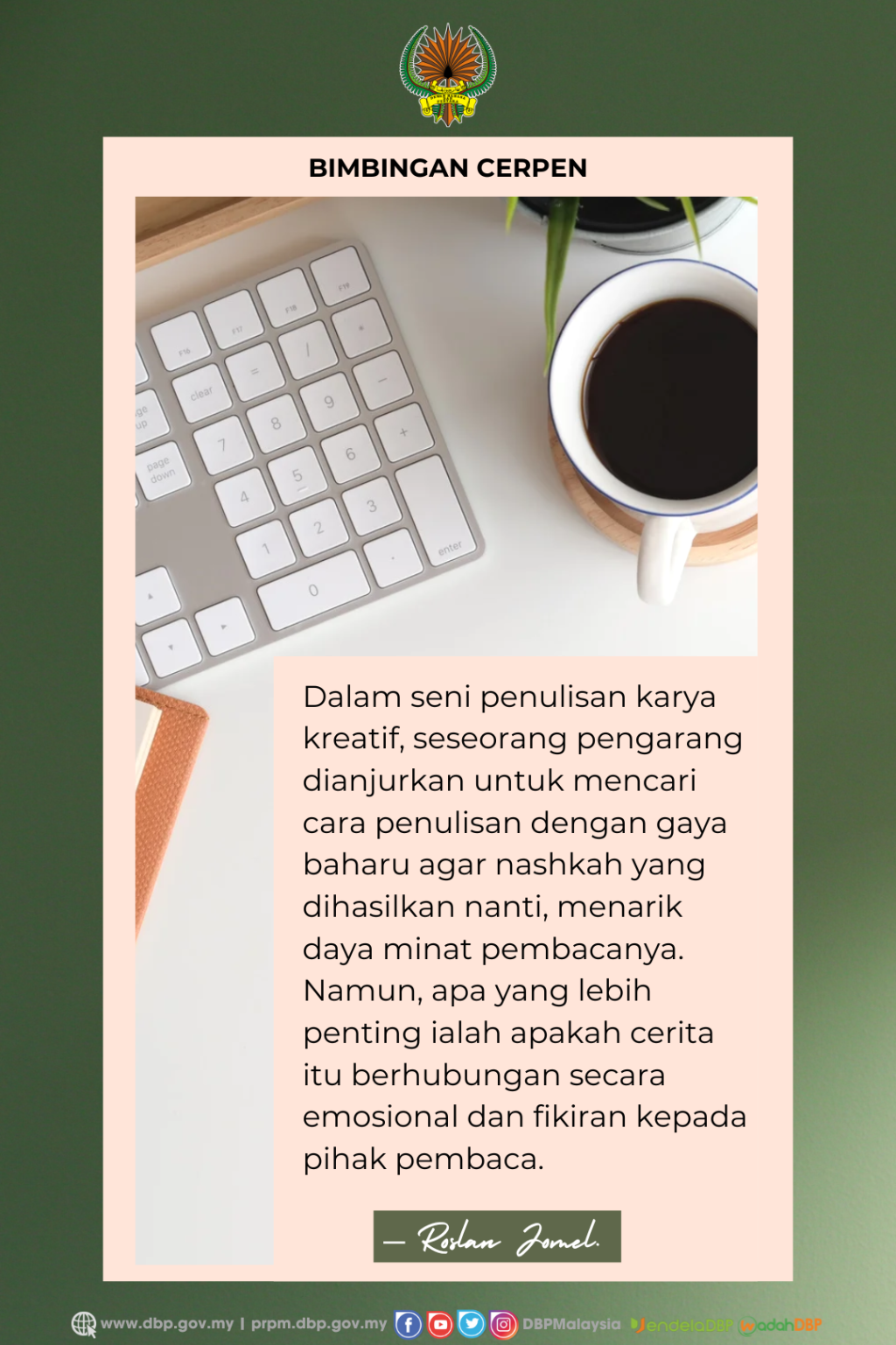

Oleh: Roslan Jomel
“Mereka memukau orang peribumi dengan jurai-jurai, kalung, manik-manik kaca, mainan berbunyi, cermin dan barang perhiasan. Dan sebagai balasan, orang peribumi itu memberi emas, hati nurani dan kebebasan yang dimilikinya.” – dipetik dari buku (terjemahan dari bahasa Inggeris) Kemalasan Peribumi Filipina, tulisan Jose Rizal, terbitan The Biblio Press, 2022.
SEBELUM masuk ke naskhah “Malik”,karya Abang Zainoren Jess, “imperialisme” menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, bermakna dasar atau tindakan sesebuah negara menjajah atau mengenakan kuasa pemerintahannya ke atas negara-negara lain. Apakah penjajahan sudah berakhir pada masa kini? Malangnya, hal demikian tetap sahaja berjalan, seiring dengan perubahan waktu dan kemajuan, penjajahan datang dengan dandanan baharu dan diberi rupa bentuk yang lebih lunak. Hanya mereka yang berfikiran kritis sahaja mampu mengesani kaedah dan helah penjajahan yang dikenakan ke atas sesebuah negara dan rakyatnya. Mungkin penindas itu datang dari negara jauh dan berambut perang, atau dalam kalangan warga sendiri.
Dan, sebagaimana dimaklumi, tiada kesudahan positif daripada kesan penjajahan ke atas sesebuah negara yang dipaksa untuk menurut segala permintaan pihak kolonial. Sama ada menanggung kerugian secara fizikal, bahkan yang paling menyedihkan apabila jiwa, pemikiran dan hak kebebasan turut direnggut. Kemerdekaan seperti apa kalau begitu? Maka tepatlah apa yang digambarkan oleh Syed Hussein Al-Attas (dipetik dari buku Imperialisme Intelektual, terbitan Lestari Hikmah, 2024), “kemerdekaan hilang apabila perahu orang putih pertama tiba dengan serbuk api dan arak. Kekacauan dan ketidakadilan membawa malapetaka. Para ketua mula menjual rakyat mereka untuk mendapatkan barang-barang.”
Semangat, sikap, karakter dan emosi yang berapi-api dalam jiwa Malik, mengembalikan saya pada tahun 1949. Negeri Sarawak, pada tarikh yang bersejarah itu, bersiap-sedia untuk menyambut dan meraikan ketibaan gabenor Duncan Stewart ke Sibu. Ketika itulah seorang anak muda, masih belasan tahun, bernama Rosli Dhoby muncul untuk memalukan imej dan lambang kebesaran (orang putih) pihak kolonial. Persis apa yang tercermin dalam pemikiran Malik ketika dimaklumkan bahawa kerajaan Brooke akan menyerahkan negeri Sarawak kepada pemerintahan koloni British. Malik, 21 tahun, tersinggung dan berasa seolah-olah negeri Sarawak bagaikan barang mainan yang boleh dijual beli sesuka hati oleh pihak asing.
Menerusi buku Kedudukan Orang Melayu Sarawak di Bawah Penjajahan British 1946-1963, tulisan Hashim Fauzy Yaacob, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, cetakan kedua, 2014, “Terdapat tiga faktor yang menyebabkan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Faktor pertama ialah berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam keluarga Brooke sendiri. Kedua, berkaitan dengan sejarah hubungan diplomatik antara Sarawak dengan Britain dan ketiga, masalah sosioekonomi Sarawak selepas pendudukan Jepun.” Vyner Brooke mengingkari janjinya sebelum ini, iaitu pemerintahan sendiri Sarawak. Disebabkan itu, gerakan antipenyerahan tercetus dalam kalangan orang Melayu. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) telah menghantar dua pucuk telegram pada 12 Februari 1946 dan 20 Februari 1946 bagi menentang langkah itu. (halaman 51).
Siapakah dan apa hak Charles Vyner Brooke untuk meletakkan negeri Sarawak kepada pemerintahan asing? Datang ke negara orang, melantik diri sebagai raja dan memperlakukan penduduk tempatan seperti bangsa primitif yang mudah diperbodoh-bodohkan. Perkara sebegitu telah mencabar darah muda yang ada dalam diri Malik. Dia tidak gentar dan mengikut sahaja helah dan permainan licik pihak penjajah. Apa urusan orang putih yang muncul entah dari mana, cuba pula untuk mengatur-atur pemerintahan negeri Sarawak? Di manakah harga diri dan maruah warga tempatan jika hal sedemikian dibiarkan begitu sahaja tanpa ada sebarang penentangan? Bagi Malik, perkara yang seumpama itu telah menjatuhkan martabat dan kedaulatan sesebuah negeri. Dia rela mengorbankan dirinya, dengan apa cara sekali pun, daripada melihat perkara itu berlaku di tanah dan negeri kelahirannya.
Tidak dapat dibayangkan, betapa jengkelnya Malik melihat beberapa orang warga tempatan yang tergamak untuk bersekongkol dengan pihak kolonial. Pegawai-pegawai tempatan yang sudah tentu dinaungi oleh pihak kolonial itu, sudah tentu terpaksa mengikut perintah daripada majikannya. Jiwa dan hati nurani mereka sudah dibeli oleh gelaran dan pangkat pemberian pihak kolonial. Mereka bagaikan perkakas kepada pihak penjajah dan tiada apa yang boleh dibanggakan dengan kedudukan mereka dalam masayarakat. Demikian juga sikap pasif seorang peniaga, yang ditunjukkan segelintir penduduk tempatan dan peniaga warung. Mereka lebih mementingkan keselesaan sementara dan keuntungan peribadi daripada terlibat dengan usaha untuk generasi masa depan. Sikap begini tetap wujud dalam masyakat sekarang.
Namun syukurlah, seramai 338 kakitangan awam dan kebanyakannya para guru, meletakkan jawatan sebagai tanda membantah tindakan penyerahan negeri Sarawak kepada pemerintahan British. Gerakan demontrasi yang kemudiannya dikenali sebagai anti-cession itu walaupun gagal mencapai matlamat untuk mengekal kemerdekaan Sarawak, namun ia telah meningkatkan kesedaran kebangsaan dan kecelikan politik dalam kalangan masyarakat Melayu di Sarawak. Hasil jerih perih, menuntut hak yang sepatutnya berada dalam tangan, sudah tentu tidak dirasai oleh generasi masa kini. Pada tarikh 16 September 1963, barulah Sarawak mengecapi nikmat kemerdekaan yang didambakan selama ini, bersamaan dengan hari pembentukan Malaysia. Apa yang diperjuangkan oleh para guru dan Malik, tidak sia-sia dan terbukti membuahkan hasil kepada negeri kelahiran.
Inilah sikap dan pemikiran yang harus sentiasa ada dalam kalangan golongan terpelajar. Bukan semata-mata berbangga-bangga dengan pendidikan tinggi dan gelaran akademik yang diperoleh. Malik mendapat inspirasi dan sokongan moral daripada keberanian sikap para pendidik. Mereka lebih mengutamakan harga diri dan kedaulatan negeri sendiri daripada mendiamkan diri demi menjaga periuk nasi masing-masing. Sungguhpun Malik tidak meneruskan pendidikan akibat pendudukan Jepun dan kemiskinan keluarga, hal itu tidak membantutkan daya kepekaannya kepada negeri sendiri. Sikap kritikal dan intelektual terserlah dalam jiwanya berbanding dengan beberapa orang pegawai tempatan yang sanggup menggadaikan negeri sendiri demi mempertahankan status quo masing-masing.
Kembali kepada struktur naskhah. Tidak dinafikan, naskhah “Malik” disampaikan dengan kemas dan ia menyerlahkan kejelasan jalan fikiran pengarang dalam mengetengahkan arah penulisannya. Aspek itu sangat penting dan menjadi kunci kepada kejayaan sesebuah naskhah. Ada pelbagai tema dan persoalan dalam sesebuah cerita yang boleh dijadikan idea penulisan seseorang. Sama ada cerita yang ringan, lucu atau yang lebih berat dan mencetuskan pemikiran seseorang pembaca kepada isu-isu penting dalam kehidupan mereka. Demikianlah apa yang telah terpampang secara visual dalam naskhah “Malik”. Ia bukan sembarangan cerita. Tetapi isi dan jiwa cerita itu terasa meresap ke dalam hati naluri pembaca yang berasa kesannya. Terasa sedih, simpati dan geram membaca naskhah “Malik”.
Secara peribadi, saya menyukai sikap dan semangat yang pengarang naskhah tanamkan dalam diri Malik. Anak muda itu benar-benar nekad, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Rosli Dhobi. Malik tidak menghiraukan nasihat rakannya, Bujang Ahim, agar jangan bertindak semberono. Bujang Ahim cuba menyabarkan Malik untuk tidak melakukan apa-apa perbuatan yang merugikan nyawa sendiri. Di mata Bujang Ahim, orang-orang tempatan, selamanya kecil dan tiada keupayaan untuk berlawan dengan pihak kolonial yang serba mencukupi. Tetapi semangat Malik tidak terpatah oleh kata-kata yang bernada pasif itu. Bangsa besar ialah bangsa yang tidak rela jiwa dan tanah air mereka dirampas oleh pihak asing. “Biarlah aku mati hari ini, asal negeriku tidak hancur…!” Demikian Malik menguatkan semangat dan keazamannya. Darah muda yang membuak-buak dalam dadanya tidak mampu ditahan lagi. Jika bukan dia, siapakah lagi hendak diharap? Jika bukan hari ini, sampai bilakah lagi?
Dari segi pembinaan cerita, tiada masalah dan kejanggalan dari sudut pengisahannya. Bahkan baik dan teratur susunan jalan ceritanya. Nama pengarang yang menghasilkan naskhah “Malik”, agak baharu kepada saya. Namun gaya dan kerja penulisan yang ditampilkan oleh pengarang tampak matang dan terkawal. Dalam seni penulisan karya kreatif, seseorang pengarang dianjurkan untuk mencari cara penulisan dengan gaya baharu agar naskhah yang dihasilkan nanti, menarik daya minat pembacanya. Namun, apa yang lebih penting ialah apakah cerita itu berhubungan secara emosional dan fikiran kepada pihak pembaca. Dan naskhah “Malik” ternyata berupaya menyelinap ke dalam sanubari pembaca. Sementelahan itu naskhah “Malik” bertema tentang insiden bersejarah dalam negeri Sarawak. Ini suatu perkembangan yang menggalakkan kepada naratif kesusasteraan kita.
Pengarang memunculkan seorang watak bernama Pak Amin, berusia 80 tahun, tetapi wawasan dan harga dirinya lebih tinggi berbanding segelintir penduduk kampung yang seolah-olah tidak mengambil peduli tentang negeri sendiri. Bagi Pak Amin, dia sudah terlalu lama hidup di bawah jajahan orang luar. Dari pemerintahan Brunei, Raja Brooke sehinggalah kepada pemerintahan kerajaan British. Apakah warga tempatan tidak layak mengurus negeri sendiri? Apakah hanya orang putih sahaja yang lebih berpengetahuan untuk mengendalikan pemerintahan? Pak Amin terlalu ingin melihat anak bangsanya yang memerintah dan mentadbir negeri sendiri. Negeri Sarawak ada pemilik asalnya. Walaupun kata-katanya disindir oleh segelintir penduduk tempatan, namun Pak Amin yakin peristiwa yang bakal berlaku semasa pengisytiharan menyerahkan negeri Sarawak kepada pemerintahan kerajaan British, akan menjadi titik mula kepada kebangkitan warga tempatan mempertahankan hak negeri mereka.
Tiada sesiapa yang berdaya melemahkan semangat Malik. Malik tetaplah Malik. Seorang patriot tulen. Tidak mempedulikan risiko yang menunggu. Sebagai warga tempatan yang sayangkan negeri dan berpandangan jauh, sikap pengecut dan pengkhianat (bermuka-muka) ditunjukkan oleh golongan elit, hanya menyemarakkan api perjuangan dalam diri Malik. Tiada sesiapa yang menyuruhnya untuk naik ke atas pentas dan merampas surat perisytiharan daripada pegawai penjajah berbangsa Inggeris. Malik sedar apa yang dilakukannya. Dia tentu maklum nasib yang menimpa Rosli Dhobi. Ini bukan masa dan tempatnya untuk menjadi hero. Tetapi sudah tiba masanya untuk seseorang dari warga tempatan untuk menunjukkan sikap dan kemahuan mereka di depan mata pihak penjajah.
Di atas pentas, Malik mengoyak surat yang menghina maruah dan harga diri masyarakat tempatan itu serta-merta. Di negeri ini, tiada sesiapa yang berhak untuk menyerahkannya kepada mana-mana pihak sebagai pemerintah. Seolah-olah negeri Sarawak tidak dihuni oleh penduduk tempatan. Tiba-tiba pihak luar datang, konon membawa kemodenan dan tamadun. Itu semua sandiwara dan pembohongan terancang. Apakah bezanya menjadi negeri naungan British kepada tanah jajahan? Statusnya tetap sahaja diikat oleh pihak asing dari luar yang tidak pun diundang. Mungkin pada detik itu, Malik tidak membaca naskhah-naskhah yang bercerita tentang kemunafikan golongan penjajah sebagaimana yang kita sempat baca pada masa kini. Tetapi Malik, beusia 21 tahun pada tahun kejadian itu berlaku, tidak perlu menjadi sarjana dan intelektual awam untuk mengesan agenda tersembunyi golongan kolonial. Akibat tindakannya, Malik ditembak di bahagian perut. Dia menghembuskan nafas terakhir dengan tangannya masih menggenggam cebisan surat perisytiharan.
Jika kita membaca buku-buku bertema sejarah, baik tempatan atau luar negara, secara ilmiahnya, sejarah telah membuktikan bahawa, tiada yang manis dalam kejadian imperialisme. Sesudah mengaut kekayaan daripada yang dijajah, mereka akan berlayar pulang ke negara masing-masing dengan kapal-kapal yang sarat dengan muatan berharga. Bagi pihak penjajah, mereka menganggap orang-orang bukan Eropah sebagai tidak berbudaya, tiada tamadun, pendidikan, daya saing, cita rasa seni dan jahil. Maka, pihak penjajah datang, baik secara solo mahupun dengan angkatan perang (perniagaan) ke tanah-tanah baharu yang dijumpai. Tidakkah kita sedar, dari buku Imperialisme Intelektual, dinyatakan bahawa warga British datang ke sini pada masa lampau hanya sekadar berkebolehan rendah berbanding dengan apa yang ada di Britain. Bayangkan warga asing dengan tahap kecerdasan yang diragui, tetapi dilantik menjadi pemerintah tertinggi dan disanjung oleh warga tempatan atas dasar hidung mereka lebih mancung dan berkulit cerah. Sungguh menyakitkan fakta itu.
Dari buku bertajuk Kesultanan Melayu Melaka, editor Azmi Ariffin, Abdul Rahman Haji Ismail dan Abu Talib Ahmad, kita akan mengerti lebih lanjut kesan negatif imperialisme yang secara amnya merupakan satu kecenderungan sesebuah masyarakat atau pemerintahan untuk mengawal masyarakat lain, biar apa pun cara dan tujuan tindakan itu. Penjajahan itu dilaksanakan melalui peperangan, penyerapan pengaruh politik melalui perjanjian, penguasaan ekonomi dan juga budaya termasuk pendidikan dan agama (halaman 22). Hal itu telah terbukti sehingga segelintir masyarakat tempatan begitu menjunjung budaya pemikiran pihak penjajah yang pernah berkuasa di sini. Lihatlah sahaja bagaimana status kecerdikan seseorang diukur dengan kebolehan berbahasa Inggeris. Jika seseorang itu tidak mahir menulis dan berbahasa kolonial, seseorang itu dianggap tidak mencapai tahap yang tinggi dalam ketamadunan dunia moden. Itulah salah satunya konsekuensi pihak penjajah menawan pemikiran warga tempatan secara halus.
Dalam naskhah “Malik”, watak utamanya mati ditembak oleh pihak penjajah. Secara estetikanya, naskhah itu berjaya menjentik rasa simpati dan kerbersamaan dengan apa yang dilakukan oleh hero itu. Rasa itulah yang mustahak dan perlu ada dalam sebarang kerja seni. Kemampuan pengarang mewujudkan elemen rasa ke dalam naskhah kreatif mereka, suatu kejayaan penting untuk menghubungkan naskhah itu secara intim ke dalam jiwa pembaca. Keberanian Malik jelas didorong oleh luapan emosinya dan hal sebegitu tentu sukar untuk dipertimbangkan daripada segi rasional. Malahan Malik sendiri menyedari risiko yang bakal menunggunya jika terus melangsaikan tindakan yang terbuku dalam jiwanya. Manakala golongan yang bekerjasama dengan pihak kolonial, kakitangan dan pegawai-pegawai berpangkat, lebih mudah dimengerti akan sikap mereka yang memilih untuk mendiamkan diri. Hidup dan zaman sudah jauh berubah, watak seperti Malik yang pemberani dan impulsif, sudah semakin jarang ditemui pada masa kini di alam nyata.
Pada tahun 1972, Queen Elizabeth singgah ke Sarawak. Jika Malik masih hidup pada ketika itu, anda bayangkan betapa pedihnya ulu hati lelaki itu. Tampaknya perjuangan patriotisme belum berhasil di negeri tercinta. Malik akan menahan tangisan di balik ribuan orang ramai yang berdiri sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera negara penjajah. Dia bergelut dengan perasaan ketika melihat perarakan dan sambutan serta hamparan permaidani merah buat menyambut delegasi yang suatu ketika dahulu memperlakukan negeri asing seperti hak milik mereka. Cebisan surat penyerahan Sarawak kepada pemerintahan British yang telah dirampas dari tangan pegawai Inggeris dahulu, kini berterbangan di udara (bersama-sama dengan ratusan belon) tetapi sebelum mencecah bumi, ia berubah bak konfeti berwarna-warni. Tanpa disedari orang ramai, Malik rebah dan mati buat kali kedua di balik kemeriahan pada hari itu.