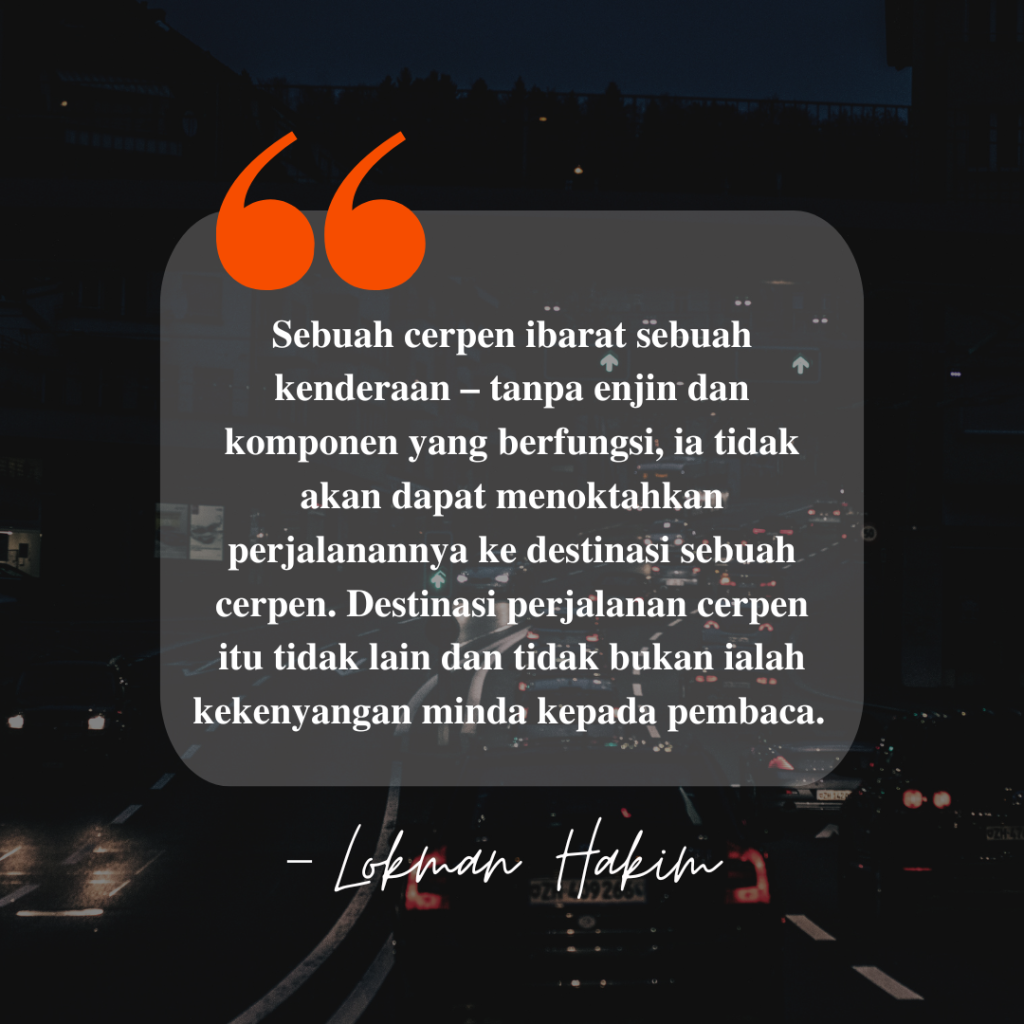

Oleh: Lokman Hakim
SEBUAH cerpen yang dikarang itu ibarat seorang penglipur lara duduk di hadapan para penontonnya lalu berkisah. Pengarang cerpen ini faham hal itu lantas menzahirkan sebuah permulaan cerpen yang baik.
Ia persis pengarang memanggil para pembacanya agar duduk di dalam penceritaan ini terlebih dahulu. Duduk, bertenang dan lupakan urusan duniawi. Sesudah itu barulah pengarang memperkenalkan dirinya selaku Medina yang mahu bercerita tentang memoir ayahnya.
Pengarang dilihat mahir dan peka dalam menjaga sudut pandang penceritaan – selaku sudut pandang pertama – pengarang hanya menceritakan perkara-perkara yang watak utama tahu dan tidak melangkau lebih daripada itu. Hal ini menunjukkan bahawa pengarang faham konsep bagaimana sebuah cerita itu harus disampaikan.
Pemerengganan dan tempo pembacaannya agak baik dan tersusun. Namun, selaku sebuah cerpen, ia harus menyajikan sesuatu yang lebih untuk menjelma sebagai sebuah cerpen yang baik.
Sebuah memoir seringkali memerangkap pengarang dalam isu pemisahan antara pengarang dengan watak. Dalam kebanyakan hal, ia tidak salah memandangkan sebuah memoir memang ditulis dari kaca mata pengarang selaku naratornya sendiri tanpa penyimpangan daripada realiti.
Di sinilah titik tolak pemisahan itu penting – penyimpangan daripada realiti ke fiksyen. Sebuah cerpen, meski bertunjangkan memoir, harus disampaikan dengan peringatan – ia harus menangkap pembaca untuk larut dalam naratifnya. Fiksyen – suatu cabang kreatif yang kerap kali menuntut tokok tambah demi menyedapkan cerita. Hatta sebuah realiti yang cukup menarik kisahnya pun menuntut pengarang untuk mahir memilih mana satu babak ataupun rincian yang harus diungkap – manakala baki selebihnya disingkirkan agar tidak mencacatkan penceritaan.
Berbalik pada cerpen “Medina untuk Abah” ini pula, dapat dikesan usaha pengarang untuk memisahkan dirinya dengan Medina, tetapi kerap kali juga, pengarang terpakai wajah Medina itu sendiri. Dialog antara Medina dengan watak Abah juga serasa direka-reka demi membangkitkan rasa sedih. Hal ini menyebabkan dialog-dialog itu terasa kurang alami dan menampakkan percubaan pengarang untuk menyedapkan naratif sebuah realiti menjadi kurang berkesan.
Terdapat keperluan untuk pengarang meneliti teks-teks dalam novel-novel melibatkan permainan psikologi mutakhir ini, yakni yang memperlihatkan perasaan dan bahasa tubuh itu sendiri diungkapkan melalui penyampaian naratif yang berkesan.
Sebagai contoh, kelakuan dua watak utama dalam filem “Abang Adik” memecahkan kulit telur dengan kepala masing-masing menjadi alat mencetuskan babak beremosi kepada para penontonnya sedangkan ia bukanlah suatu babak yang luar biasa atau aneh.
Ataupun dalam siri drama Korea “Reply 1988”, penonton dipersembahkan dengan begitu banyak bahasa tubuh watak-wataknya demi mengungkapkan emosi penceritaan.
Saya melihat kelemahan dalam garapan dialog pengarang cerpen “Medina untuk Abah” ini dan percaya bahawa kelemahan itu boleh diperbaiki seiring dengan waktu dan usaha pengarang untuk menjadi penulis yang lebih baik.
Namun, secara alternatifnya, pengarang boleh merujuk filem dan drama yang disarankan untuk memahami potensi bahasa tubuh dalam menyampaikan sebuah fiksyen memoir yang menyentuh hati.
Dalam erti kata lain, pengarang harus lebih mahir dalam memilih rincian dan babak yang sesuai untuk mendukung naratif sebuah memoir yang berkesan nostalgia dan kesalnya.
Meskipun begitu, pembinaan karakter kepengarangan dalam cerpen ini agak baik. Cerpen ini mengungkapkan personaliti kepengarangan yang jelas – pengarang punya karakter narator yang tenang, memilih untuk bergerak dari satu babak ke babak secara kronologi dan tidak semberono menambah rincian yang tidak perlu. Ketenangan dalam garapan naratif ini kelihatannya sebati dan alami – suatu perkara yang harus dipuji pada penulis pemula seperti ini.
Kebijaksanaan pengarang – harus dipupuk supaya ayat disusun lebih dramatik dan berkesan.
“Malam itu terasa sangat asing. Selalu kerusi luar itu diisi oleh abah. Malam ini ia kosong, sunyi dan dingin. Adakah ini rasa abah sepanjang ketiadaanku? Masih ada bayang gelak tawa kami di setiap sudut rumah.”
Jika ditelusuri ayat-ayat di atas, ia tidak janggal. Bahkan ia mengungkapkan dengan jelas perasaan yang watak utama lalui dalam cerpen ini. Tragedi ditulis dengan pelbagai cara. Kedewasaan dalam kepengarangan akan membawa pengarang ke arah pemilihan kata-kata yang lebih tepat dan juga perumpamaan kesakitan yang diakibatkan tragedi supaya ia lebih membekas.
Justeru, bagaimanakah sifatnya “kosong, sunyi dan dingin” itu? Menulis sekadar tiga perkataan itu tidak memadai untuk menjelaskan inti pati perasaan yang hendak disampaikan kepada pembaca.
“Kosong” sebuah kotak yang membungkus barangan yang dibeli melalui kedai dalam talian tidak mungkin sama dengan “kosong” sebuah rumah yang hendak ditinggalkan setelah didiami selama tiga generasi.
“Sunyi” seorang Medina yang baru sahaja melanjutkan pelajaran ke luar negeri tidak sama dengan “sunyi” ayahnya yang ditinggalkan di rumah.
Pemilihan babak-babak selaku alat membina tujuan sesebuah cerpen ditulis amat penting. Dalam cerpen “Medina Untuk Abah”, penulis memecahkan penceritaannya kepada empat latar waktu berbeza.
Babak pertama membawa maksud pengarang untuk menjelaskan falsafah di sebalik susah payah seorang bapa mendukung tanggungjawabnya. Babak kedua pada latar waktu dua tahun sesudahnya, pengarang cuba menggambarkan situasi Medina berpisah dengan keluarga – ketika itu, jarak masih membangkitkan rasa rindu menebal si anak terhadap keluarga.
Babak ketiga pula berlaku pada latar waktu tiga tahun sesudahnya, iaitu ketika Medina, yang sudah terbiasa berjauhan dengan keluarga mula diracuni situasi kebiasaan itu – kehidupan baharu sudah menjarakkan dirinya daripada kerap berhubung dengan keluarga tersayang. Pengarang kelihatannya pintar membina transisi watak Medina dengan baik dengan babak demi babak ini.
Babak keempat pula berlaku pada latar waktu lima tahun sesudahnya, yakni semasa tragedi menimpa keluarga Medina dengan kematian ayah. Ia menjernihkan kembali rasa hambar akibat jarak yang menjerumuskan Medina dalam kedinginan perasaan terhadap keluarga, lantas menjadi asbab utama pembentukan cerita ini.
Kita dapat melihat bagaimana pengarang pemula ini begitu faham apa yang hendak disampaikan melalui transisi penceritaan yang sederhana dan terkawal temponya ini. Namun, bagaimanakah pula dengan cara sesebuah babak itu diceritakan? Atau kita boleh bertanya pada diri, adakah terdapat cara penceritaan yang lebih baik untuk cerpen serupa memoir ini?
Dalam babak pertama, pengarang menggunakan situasi di meja makan. Ketiadaan si ibu dek kesibukan bekerja selaku jururawat pada sebelah malamnya menuntut si ayah untuk mengambil alih tugas menjaga makan minum keluarga meskipun sudah penat bekerja pada sebelah siangnya. Ia disusuli dengan dialog sesudah makan malam dan solat. Di sini, falsafah kebapaan dirungkaikan dalam perbualan anak-beranak itu.
Naratif cerpen ini akan lebih menarik sekiranya pengarang tidak menggunakan dialog selaku alat menyampaikan falsafah kebapaan itu. Ia kelihatan seperti terlalu berkhutbah lantas menempelkan imej hambar pada watak ayah yang digambarkan dalam cerita ini. Seandainya pengarang memilih untuk fokus pada tindakan demi tindakan si ayah, diungkapkan jerih-perihnya menyelesaikan urusan keluarga mendahului kehendak peribadi, naratifnya akan lebih mengesankan untuk pembaca jatuh simpati dan kagum pada susuk “Abah” dalam penceritaan ini.
Dalam babak kedua pula, rasa kerinduan yang cuba digambarkan melalui dialog antara Medina dan kedua-dua orang ibu bapanya rasa kering dan tidak hidup. Ia barangkali diakibatkan ketiadaan bahasa tubuh si ayah dan si ibu dalam naratif pengarang. Watak “Abah” seolah-olah satu dimensi – tiada sisi kelabu mahupun kelemahan yang membuatkan wataknya kurang hidup. Seorang yang baik tidak semestinya terlepas dari perbuatan rajuk, marah, cemburu ataupun paling tidak pun berdiam dan menyendiri tanpa penjelasan nyata.
Apabila pengarang meletakkan pekerjaan si abah selaku penyelidik di pusat Falak berserta minat terhadap bidang astronomi, saya melihat potensi penceritaan pengarang menggunakan minat si abah yang tidak kesampaian ini selaku alat pembinaan watak. Barangkali, demi menghidupkan penceritaan, digambarkan pula kecenderungan si abah mengumpul objek-objek bertunjangkan astronomi atau untuk lebih mengesankan, si abah ditemukan sudah memajak barang-barang hobinya di kedai pajak demi memastikan tabung pendidikan Medina ke universiti mencukupi.
Dalam babak ketiga pula, pengarang kelihatannya ghairah mahu mengungkapkan tragedi kematian si abah tanpa menyedari logik fiksyen yang dilanggar ketika mengarang.
Benar, watak Medina ibarat kacang lupakan kulit, tidak menjawab panggilan dari keluarganya walau bertali arus panggilan dibuat. Hal ini tidak dibinakan premisnya dengan baik. Jarak dan kesibukan semata-mata tidak akan mengubah sikap anak terhadap ibu bapa melainkan terdapat suatu permasalahan akar yang berkembang menjadi kedinginan seperti yang ditunjukkan watak Medina ini.
Secara logiknya, 30 panggilan bertali arus tidak berjawab menzahirkan keperluan untuk ia dibalas dengan kadar segera dan bukannya dibuat atas dasar “rindu” semata-mata. Adalah aneh untuk watak tersebut, yang juga seorang yang terpelajar memutuskan untuk tidak membalas panggilan setelah menyedari ada 30 panggilan tidak berjawab.
Babak penamat, iaitu babak keempat yang berlaku lima tahun sesudah kematian abah begitu ringkas digarap. Tiada salahnya pada ringkas sebuah penamat tetapi ia tidak mendukung naratif dan tujuan asal cerpennya ditulis. Tambahan pula ia diladeni nasihat yang kedengarannya seperti berkhutbah lantas menghilangkan kemanisan sebuah fiksyen.
Ketika dihidangkan dengan cerpen ini, saya menyimpulkan meskipun pengarang ini baru bermula, dia tidak naif bahkan punya sedikit ilmu mengarang. Rukun sudut pandang dipatuhi, penjagaan tempo penceritaan juga amat kemas diiringi transisi watak utama yang tampak jelas dari satu babak ke babak yang lain. Namun, sebuah cerpen yang kuat haruslah bertunjangkan permasalahan yang mengakar realiti semasa masyarakat. Konflik yang dibina di dalam cerpen ini tiada keunikan memandangkan ia hanya menyentuh permukaan masalah utama dalam masyarakat. Keluarga Medina ini juga bukanlah keluarga yang dihimpit kesusahan fizikal lantas menuntut keperluan untuk pengarang menelusuri dan menggarap sebaiknya emosi setiap watak-wataknya yang tampaknya hanya berat pada watak utama, Medina sahaja.
Oleh demikian, berdasarkan asas kepengarangan yang kuat, pengarang harus menelusuri bahan-bahan sarat pemikiran dan banyak mempersoal hal-ehwal kehidupan demi memberi kedewasaan dalam garapan cerita-cerita yang akan datang.
Di samping itu, melihat kepada kecenderungan pengarang menulis realisme, maka haruslah pengarang mempelajari ungkapan emosi manusia melalui bahasa tubuh.
Potensi pengarang untuk mencipta gagasan memoir yang berkesan terlihat jelas melalui penceritaan yang ringkas tetapi padat. Barangkali, ia harus dibungai dengan laras bahasa sastera dengan iringan fokus pada matlamat penceritaan yang mahu menyampaikan sesuatu dengan kosa kata yang tepat dan mampu mendukung maksud dengan sejumlah ayat optimum.
Berlandaskan tujuan sebuah cerpen digarap, setiap babak demi babak yang mahu diserapkan ke dalam sebuah penceritaan harus disemak kembali keperluannya, sama ada bercanggahan atau bergerak selari dengan tujuan cerpen tersebut. Harus diingatkan, sebuah cerpen ibarat sebuah kenderaan – tanpa enjin dan komponen yang berfungsi, ia tidak akan dapat menoktahkan perjalanannya ke destinasi sebuah cerpen. Destinasi perjalanan cerpen itu tidak lain dan tidak bukan ialah kekenyangan minda kepada pembaca.