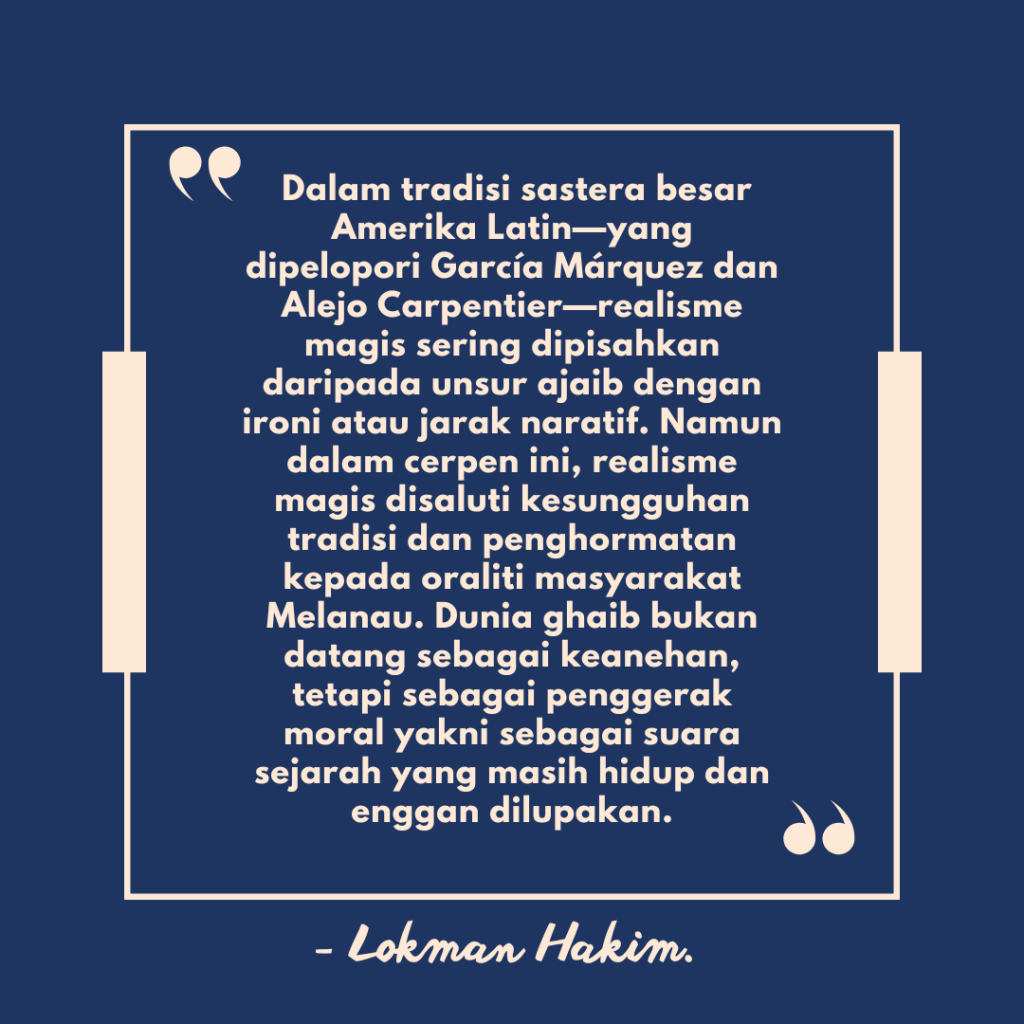

Oleh: Lokman Hakim
SEJUJURNYA, membaca cerpen “Pasir Dua Belas” yang ditulis Adie Abd Gani ini menemukan saya dengan garapan sebuah cerpen budaya yang seimbang meter pembacaannya. Ayat-ayatnya digarap dengan matang, kosa katanya cemerlang dan ungkapan-ungkapan perihal budaya nelayan di Kuala Matu, yakni elemen kearifan tempatan tampaknya dicermati sebaiknya. Dalam erti kata lain, ini bukan cerpen seorang penulis pemula. Justeru, ulasan ini bersifat suatu perenungan yang harapnya ditanggapi pengarang cerpen ini untuk memperluaskan lagi spektrum kepengarangan sedia ada.
Membaca sekali harung, dapat dirasakan pengaruh SN Arena Wati, yang diketahui sangat akrab dengan laut. Kita boleh menemukan babak mencandat sotong dalam karya Arena Wati lalu mencecap kelazatan nostalgianya tanpa mengetepikan kelantangan suara politikal nan keras dalam karya-karya sasterawan negara itu. Jika dilihat dari aspek itu, saya berpendapat Adie Abd Gani boleh meneroka sisi tersebut – suara politikal yang dijalin halus dengan keindahan gaya bahasa sedia adanya dan roh kearifan tempatan yang perkasa dalam tulisan sebegini.
Pengarang boleh melihat sendiri jaringan pengangkutan yang ligat dibina di Sarawak dengan jangkaan spekulatif – sekali gus menulis sebuah karya yang menyumbang kepada idea-idea gagasan pembangunan yang wajar diangkat demi memakmurkan Sarawak. Namun ini hanya suatu cadangan dan sesebuah karya sastera tidak harus terlalu lantang nada politikalnya hingga hilang keindahan sasteranya.
Berbalik pada cerpen ini, ada sesuatu yang mendalam dan tak terucap yang mengalir seperti arus laut di balik naratifnya. Seperti laut Kuala Matu itu sendiri—yang tampak tenang tetapi menyimpan kekuatan ghaib yang mampu menelan beting dan manusia dalam sekelip mata—begitulah juga prosa Adie Abd Gani: tenang dalam permukaannya, namun bergejolak dengan makna dalamannya.
Cerpen ini menandakan satu tahap kematangan dalam penulisan realisme magis Malaysia yang mengakar daripada lokaliti, bukan sekadar estetika eksotik atau tempelan budaya. Adie tidak sekadar menulis tentang Kuala Matu; beliau memanggil semangatnya ke dalam halaman, menjelmakan bukan sahaja ruang geografi tetapi juga ruang spiritual, adat dan mitos yang menyelubunginya.
Dalam tradisi sastera besar Amerika Latin—yang dipelopori García Márquez dan Alejo Carpentier—realisme magis sering dipisahkan daripada unsur ajaib dengan ironi atau jarak naratif. Namun dalam cerpen ini, realisme magis disaluti kesungguhan tradisi dan penghormatan kepada oraliti masyarakat Melanau. Dunia ghaib bukan datang sebagai keanehan, tetapi sebagai penggerak moral yakni sebagai suara sejarah yang masih hidup dan enggan dilupakan.
Ben, watak utama, membawa seluruh struktur naratif di bahunya, namun bukan sebagai narator yang mahu menuntut simpati, sebaliknya sebagai penjaga sunyi sebuah perwarisan. Nama penuhnya, Benedict S. Amling, begitu ironi dalam dirinya: seorang Bidayuh yang hidup dalam komuniti Melanau, menjadikan identitinya satu bentuk jambatan antara budaya. Namun Adie tidak menjadikan hal ini sebagai tema perpecahan; sebaliknya, ia menjadi penegasan bagaimana adat dan warisan melangkaui garis-garis etnik menjadi tanggungjawab sesiapa sahaja yang hidup di dalamnya.
Struktur naratif yang bergerak daripada kenangan lalu ke arah konflik kini dan kemudiannya menuju ke tragedi mendatang, dilangsungkan dengan ketelitian yang tidak terburu-buru garapannya. Cerpen ini tidak ditulis dengan tergesa-gesa. Adie menulis dengan kesabaran seorang pendongeng tua di tepi pantai yang tahu bahawa cerita yang baik memerlukan ruang untuk bernafas. Perenggan-perenggan awal dipenuhi dengan pemerhatian puitis terhadap laut dan perahu serta hubungan antara Ben dengan Clayton. Malah tawa Clayton— “seperti ombak menghempas tebing pasir di Kuala Matu”—muncul sebagai motif berulang, iaitu suatu gema daripada masa lalu yang mengganggu masa kini.
Clayton hadir sebagai antitesis kepada Ben. Jika Ben adalah laut yang bersabar dan mendalam, maka Clayton adalah angin kencang yang mahu melawan laut. Tetapi Adie tidak menulis Clayton sebagai antagonis klise. Sebaliknya, Clayton ialah anak watan yang tercabut daripada akarnya—dan kecabutan itu menjadikan dia skeptikal terhadap apa-apa yang suatu ketika dahulu melindungi jati dirinya mahupun manusiawinya. Dalam dunia moden Malaysia, watak seperti Clayton sangat relevan: generasi yang mungkin dibesarkan dengan kisah-kisah adat tetapi kini mempersoalkannya, menolaknya, malah memperlekehkannya atas nama kemajuan atau rasionalisme.
Namun kekuatan Adie sebagai penulis adalah pada keengganannya memukul palu penghakiman. Clayton tetap diberikan ruang pengampunan—dia tidak dihukum secara tuntas, malah dibenarkan menebus dosa melalui tindakan membina semula pondok laut milik Ben. Dalam kebanyakan naratif realisme magis, kita jarang melihat ruang untuk pembaikan setelah pelanggaran adat itu berlaku. Tetapi dalam cerpen ini, selepas tragedi, terdapat kesedaran. Dunia ghaib di Kuala Matu bukan ditanggapi selaku pendendam, tetapi selaku guru yang mahu didengari lalu diambil iktibar setiap ajarannya tentang alam.
Perihal deskripsi ruang, Adie menulis dengan kekayaan pengamatan dan keterikatan emosi. Pantai Kuala Matu, beting Pasir Dua Belas, pondok laut, kapal tunda, bahkan lidi dan kapur—semua ini bukan hanya latar, tetapi objek-objek naratif yang menyimpan nilai, sejarah dan tanda amaran. Di tangan penulis yang kurang teliti, semua ini akan menjadi seperti katalog budaya. Tetapi Adie menjadikan setiap satu unsur sebagai alat penceritaan: lidi sebagai metafora hubungan manusia dengan alam, dan kapur yang menjolok ambal sebagai simbol perbuatan manusia terhadap rezeki—menyentuhnya harus dengan niat yang baik, atau malapetaka menanti.
Bahasa yang digunakan dalam cerpen ini memperlihatkan penguasaan Adie terhadap nada dan tekstur. Terdapat ekonomi dalam gaya, tetapi tidak mengorbankan keindahan. Ada ayat-ayat yang bergetar persis mantera, misalnya: “Ah! Betapa itu semua hanyalah kenangan yang telah lama berlalu pergi bersama angin laut, menyisakan asinnya di benakku.” Ini adalah suara naratif yang puitis, tetapi tidak berlebihan—sejenis gaya yang James Wood sendiri sanjungi: gaya yang “memiliki muzik dan makna dalam masa yang sama.”
Malah penggunaan kosa kata tempatan—palei, sesar unjur, pisak tibou, uyan—ditangani dengan cermat dan kontekstual. Glosari di akhir teks adalah satu pendekatan yang halus; ia tidak memaksa pembaca luar budaya untuk memahami semuanya serta-merta, tetapi memberi ruang agar pembaca mendekati dunia Melanau seperti kita mendekati laut: langkah demi langkah.
Perkara yang menjadikan cerpen ini sangat kuat dalam rangka realisme magis ialah keberaniannya untuk tidak bersifat ‘ajaib’ demi keajaiban semata-mata. Dalam cerpen ini, tragedi yang berlaku bukan kerana sebarang makhluk ghaib muncul secara harfiah atau dramatik. Tiada pontianak, tiada jelmaan naga laut mahupun rasukan dewa laut. Sebaliknya, kekuatan ghaib ialah palei itu sendiri—pantang larang yang dijelmakan sebagai manifestasi kolektif masyarakat terhadap nilai, moral dan penghormatan kepada rezeki, yakni suatu kelaziman dalam budaya orang Asia keseluruhannya. Dan apabila palei dilanggar, yang bangkit ialah laut itu sendiri, dengan caranya yang realistik tetapi juga sarat simbolik.
Inilah kekuatan utama naratif ini: ia mengajarkan kita bahawa ‘magis’ tidak harus datang dari luar hukum dunia, tetapi boleh juga terbit dari hukum moral yang dilanggar. Ketawa berlebihan terhadap rezeki, memperlekehkan ambal sebagai alat kelamin kera—semua ini ialah dosa kecil yang dibalas oleh alam bukan kerana dendam tetapi kerana keadilan moral. Dunia ini tidak dibina atas kontrak sosial manusia semata-mata, tetapi kontrak ghaib antara manusia dengan alam.
Penutup cerpen ini tidak menutup pintu kepada pembaca. Sebaliknya, ia membuka jendela baharu untuk refleksi. Pondok laut yang dibina semula bukan sekadar struktur fizikal, tetapi menjadi ruang peringatan. Ia adalah muzium hidup kepada tragedi Pasir Dua Belas. Tetapi lebih daripada itu, ia adalah ruang pemulihan hubungan manusia dengan laut, adat dan sesama manusia.
Clayton yang berubah, yang akhirnya meminta maaf dan membina semula pondok laut Ben, bukan hanya insaf kerana nyaris maut, tetapi kerana menyedari bahawa warisan bukan benda yang boleh dimodenkan sewenang-wenangnya. Adat bukan sesuatu yang antik dan boleh diabaikan meski zaman beredar dan berubah. Ia adalah perjanjian kolektif yang hidup dan hidup terus apabila kita mendengarnya, menuturkannya dan mewariskannya.
Dalam dunia sastera yang semakin diasak oleh suara metropolitan, globalisme dan dekontekstualisasi budaya, naskhah “Pasir Dua Belas” berdiri teguh sebagai naratif yang menolak kealpaan. Ia mengangkat suara tempatan bukan sebagai dongeng rakyat, tetapi sebagai falsafah hidup yang relevan dari masa ke semasa. Dalam pendekatan Adie, cerpen ini bukan sekadar cerita tentang laut dan tragedi. Ia adalah meditasi tentang hubungan antara manusia dan alam, tentang pengajaran yang tidak hadir daripada buku teks tetapi daripada lidah orang tua yang telah lama diam dan daripada tanah pasir yang sesekali menjelma untuk memberi rezeki—dan peringatan.
Seperti ujaran James Wood dalam The Broken Estate, “Fiction should liberate truth from mere fact.” Dan “Pasir Dua Belas” telah melakukan pembebasan seumpama itu. Ia membebaskan kebenaran—tentang adat, tentang manusia dan tentang kehancuran akibat kesombongan—daripada sekadar fakta. Ia menjelmakan kebenaran itu dalam bentuk cerita yang hidup, menggugah dan membekas.
Apabila kita cuba melihat sisi lainnya, yakni potensi untuk ia ditulis semula dengan cara yang lebih baik, saya melihat bahawa cerpen ini ialah sejenis teks yang membawa kita berjalan di pinggiran dunia. Dunia yang belum sepenuhnya ghaib, tetapi juga bukan sepenuhnya nyata—satu kawasan peralihan antara tanah dan laut, adat dan keberanian moden, warisan dan kesangsian. Ia dibina dengan ketekunan seorang penulis yang benar-benar mencintai tempat asalnya, atau sekurang-kurangnya mencintai idea bahawa tempat seperti Kuala Matu masih ada, masih hidup, masih mampu membalas apabila diketawakan.
Namun seperti mana-mana tanah pasir yang sentiasa berubah bentuk ketika dilanggar ombak, cerpen ini sendiri memaparkan bentuk-bentuk yang kadang stabil, kadang longgar dan kadang seolah menunggu runtuh. Keindahan naratif yang mendalam ini sesekali terasa seperti ditanggung oleh rangka dramatik yang belum sepenuhnya padat, seolah-olah benang-benang tema dan wataknya belum benar-benar ditarik hingga hujung simpulan.
Ada ketelitian yang luar biasa dalam membina dunia Kuala Matu—lidi, kapur, bakak, palei, sesar unjur—semuanya bukan hiasan eksotik tetapi dijelmakan sebagai peralatan moral dan metafora. Namun, apabila pembacaan terus berjalan, kita mulai terasa bahawa segala perincian budaya ini kadang-kala tidak sepenuhnya dirangkum ke dalam naratif yang mengalir secara dramatik. Ia seolah-olah diletakkan seperti nota kaki dalam badan teks, sebuah katalog yang terselit dalam alur cerita. Pembaca barangkali tidak akan rasa keberatan pengungkapannya—kerana dunia itu menarik garapannya—tetapi ketegangan dramatik yang patutnya semakin menegang, sesekali direnggangkan oleh penceritaan informatif. Ironinya, adat dan tradisi yang menjadi nadi cerita ini kadang-kadang muncul bukan melalui darah dan konflik watak, tetapi melalui penjelasan. Ia seperti seorang tok batin yang tiba-tiba memegang mikrofon, menjelaskan segala simbol yang penonton mungkin belum faham.
Kita mengikuti Ben dengan simpati, namun jarang benar kita benar-benar merasai denyut batinnya. Dia tampil sebagai watak yang tekal, tenang, teguh, seorang pelindung adat—tetapi seorang watak tidak cukup hidup hanya dengan menjadi lambang. Kita ingin tahu lebih tentang ketakutannya yang terdalam, bukan hanya pada ombak dan sumpah nenek moyang, tetapi tentang dirinya sendiri. Apakah erti menjadi satu-satunya Bidayuh dalam komuniti Melanau itu? Apakah ia hanya nota latar atau benih kepada rasa keterasingan yang terpendam? Kita diberitahu tentang peranan bapanya, tentang kenangan bersama Clayton, tetapi tidak cukup dibawa masuk ke dalam ruang batin Ben yang lebih rapuh. Seolah-olah, dia tahu segala aturan laut dan adat, tetapi tidak sepenuhnya diperlihatkan bagaimana dia menanggungnya sebagai manusia, bukan hanya pewaris.
Clayton pula, dengan segala keangkuhan dan kepulangannya, berperanan sebagai pencetus krisis—namun kedegilan dan transformasinya terasa agak dikendalikan dari luar. Kita tidak diberi kesempatan untuk menyelami benar perubahan dalaman watak ini. Dia menolak adat, mentertawakan ambal yang melompat dari pasir seolah ia “alat kelamin kera”—dan kemudian, selepas tragedi, memohon maaf, membina semula pondok dan kembali berdiam. Tetapi perubahan ini terlalu rapi. Di dunia sebenar, trauma sering meninggalkan kesan yang tidak dapat ditampung dengan hanya satu tindakan simbolik. Ia tinggal sebagai bisikan, sebagai mimpi buruk, sebagai kegagapan dalam menutur kata kepada mereka yang kita lukai. Di sinilah cerpen ini sedikit terlalu yakin dengan penutupnya—ia terlalu pasti tentang pengampunan, terlalu bersih dalam penyelesaian.
Terdapat juga ironi dalam struktur dramatik yang barangkali tidak disengajakan: bahagian awal cerpen memerlukan kita bersabar, perlahan-lahan melayari gelora kenangan sambil menunggu ombak sebenar datang. Dan apabila ia datang—ketika bah besar dan tragedi mula menimpa beting pasir itu—cerpen ini berubah menjadi sejenis penceritaan yang hampir sinematik: jeritan, angin yang mengganas, camar yang lesap dari langit, perahu yang teroleng. Dan walaupun dramatik ini diusahakan dengan bersungguh-sungguh, pembaca yang peka mungkin terasa terlempar dari dunia puitik yang sebelum ini begitu berbisik, masuk ke dalam ledakan visual yang hampir seperti skrip filem. Dalam dunia naratif seperti ini, kita lebih percaya kepada tragedi yang datang senyap-senyap, yang meresap dalam diam yang menyelinap dalam tubuh watak seperti sejuk air laut yang tidak terasa melainkan setelah menggigil.
Namun bukanlah kelemahan ini suatu kegagalan, bahkan ia menandakan betapa banyaknya ruang dan potensi yang boleh dimanfaatkan oleh penulis. Cerpen ini, seperti pondok laut Ben sendiri, telah dibina dengan penuh kasih dan kerja tangan—tetapi sedikit kurang teguh pada beberapa tiangnya. Mungkin pondok itu perlu lebih lama diasak angin, lebih banyak disandar beban, lebih sedikit menjerlus dan kurang sempurna dalam simetrinya—agar pembacaan kita terhadapnya juga menjadi lebih organik, lebih menyerupai hidup.
Bahkan penutupnya—yang menjadikan pondok laut sebagai ruang penyebaran legasi, sejenis muzium kecil kepada tragedi—membawa kita kepada semacam harapan yang terlalu tersusun. Kita percaya pada pencerahan, tetapi jarang pencerahan berlaku dalam garis lurus. Mungkin akan lebih mengganggu dan lebih menyentuh jika cerpen ini berakhir dengan sesuatu yang tergantung: misalnya, suara Clayton yang tidak pernah Kembali atau Ben yang hanya duduk di pondok itu seorang diri saban musim tengkujuh, menunggu ombak yang tidak sempat ditenangkan.
Namun demikian, harus diakui: “Pasir Dua Belas” ialah cerpen yang tahu ke mana ia mahu pergi, dan tahu tanah mana yang mahu dipijaknya. Ia tidak mahu memukau pembaca kota dengan keajaiban tempatan yang penuh eksotisme. Ia mahu memberitahu bahawa tanah kecil seperti Kuala Matu menyimpan undang-undangnya sendiri, dan undang-undang itu bukan ditulis dalam papan tanda, tetapi dalam tindak-tanduk, pantang larang dan deru ombak. Dan apabila seseorang ketawa terlalu kuat terhadap makhluk kecil yang keluar dari pasir, seluruh alam akan senyap dan menunggu. Menunggu siapa yang akan hanyut, dan siapa yang akan kembali dengan sesal.
Dalam sunyi yang ditinggalkan oleh cerpen ini, kita mendengar bukan sahaja gelombang laut yang kembali menelan pasir, tetapi juga bunyi-bunyi kecil kelemahan cerpen ini sendiri—bunyi yang tidak menjatuhkan, tetapi mengingatkan bahawa setiap cerita, seperti setiap ombak, boleh diulit semula, diperbaiki dan diberi bentuk yang lebih dalam. Bukan demi kesempurnaan, tetapi demi kehidupan yang lebih jujur.