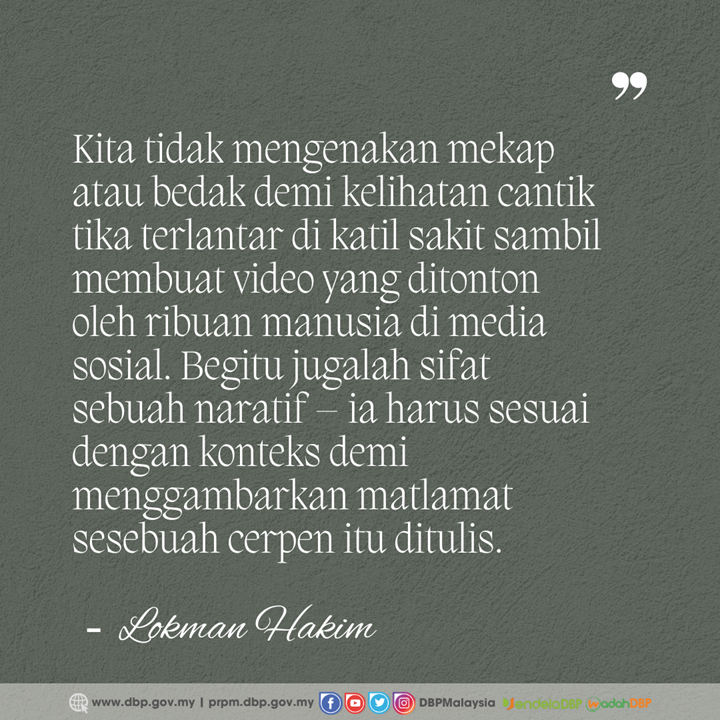

Oleh: Lokman Hakim
SECARA teknikalnya, ia sebuah cerpen yang baik. Secara ringkasnya, cerpen ini cuba mengungkap penderitaan seorang ibu mendepani kematian anak yang baru dilahirkan seiring dengan kematian suami dalam sela waktu yang begitu singkat. Tragedi berganda. Pengarang berusaha memberi perhatian kepada perkembangan emosi dan gejolak dalam jiwa watak utama. Rintih watak utama, Mira, cuba digambarkan sebaik mungkin. Meskipun secara teknikalnya, pengarang mematuhi rukun-rukun cerpen yang baik, pemilihan perkataan merupakan isu yang besar dalam usaha pelukisan latar cerita yang sepatutnya memilukan ini.
“BUKAN! Itu bukan anak kau!” Tingkah kumpulan suara asing yang membentak di mindaku, berkali-kali. Bengang. Sudah seminggu aku terkurung berkecamuk. Serabutnya bagai tajam pisau membelati luka yang sudahpun berdarah.
Begitulah ayat pemula yang memacu perenggan demi perenggan. Pembaca dibawa mendepani monolog demi monolog dalam kepala seorang penghidap kemurungan pascapartum.Di sinilah yang ingin saya tekankan, pemilihan naratif sebegini akan merencatkan konteks pelukisan kepiluan yang cuba digambarkan.
“Mengerti auraku akan mati tersungkur menerima kecaman sebegitu.”
Kecenderungan pengarang menerapkan jargon-jargon janggal demi memaparkan kekayaan kosa katanya tampak tidak natural. Apa yang dimaksudkan dengan “auraku akan mati tersungkur”? Sekali imbas, dapat dirasakan pengarang cuba menggambarkan sifat pergelutan dengan suara asing dalam diri. “Aura” yang dimaksudkan itu barangkali “jiwa” atau “semangat” tetapi menggandingkan ia dengan “mati tersungkur” agak aneh.
“Jelingannya membuatkan hatiku berbuku.”
Ayat “hatiku berbuku” menghadirkan tanda tanya. Bagaimanakah sifatnya “hati” hendak digandingkan dengan “berbuku”? Terma yang lebih tepat barangkali “hatiku berbulu” yang menggambarkan rasa sakit hati yang mendalam terhadap sesuatu.
“Terasa duniaku seakan berputar, melontar pandangan cemuh kepadaku.”
Menggandingkan “pandangan” dengan “cemuh” sebenarnya tidak perlu. Bahkan dalam konteks ayat di atas, perkataan “pandangan” itu telah merencatkan keindahan ayat tersebut dengan mendukung perkataan yang tidak membantu memperkukuh makna ayat.
“Acapkali lembaga yang mendakwa berasal dari kampung bunian di pinggir hutan berkeras mahukan anak aku menyinggah pandangan.”
Memasukkan elemen mistik dalam sebuah cerpen yang kelihatannya mahu mengangkat permasalahan jiwa tidaklah bersalahan. Tetapi ia menuntut pembinaan latar cerita sampingan demi menyokong alur penerapan elemen mistik tersebut. Maka, naratif cerpen yang terhad barangkali tidak mampu menyokong gagasan pembinaan naratif sampingan begini.
Boleh sahaja diterapkan elemen bunian ini. Entiti ghaib itu mungkin dijadikan penggerak utama permasalahan dan bukannya tragedi berganda. Pascapartum yang dikaburi tipu muslihat bunian. Seawal naratif, pengarang harus menggaitkan tuntutan bunian ke atas si anak yang dilahirkan dengan beberapa isyarat-isyarat mistik.
Semestinya cerpen yang kelihatannya bertunjangkan hasrat pengarang yang mahu mendidik pembaca mengenai istilah perubatan yang berkaitan dengan pascapartum depresi akan lari dari tujuan. Oleh hal yang demikian, haruslah disingkirkan sahaja elemen bunian mahu menuntut si anak daripada cerpen ini.
Tidak dinafikan lagi pengarang bukan sekadar kaya dengan kosa kata tetapi mahir juga dengan perlambangan demi perlambangan demi menggambarkan emosi pesakit pascapartum dengan keindahan bahasa. Oleh itu, saya terdorong untuk menelusuri sedalam manakah “kebiruan” hari sepi yang cuba digambarkan pengarang.
Pada tahap ini, pengarang boleh dikira sebagai seorang yang berpengetahuan untuk mengarang sebuah cerpen yang baik. Namun sebaik manakah cerpen itu ditulis? Sedalam mana kefahaman pengarang terhadap isu depresi pascapartum yang pastinya tidak akan dilalui pengarang sendiri secara peribadi?
“Naluri keibuanku kembali menerjah supaya menghampiri Qaiser lalu dakap memujuk.”
Sebermula dari sini, saya memikirkan suatu sisi, iaitu kepada siapa cerita ini diceritakan dan oleh siapa? Memandangkan ia ditulis daripada sudut pandang pertama, wajarlah dikatakan ia ditulis daripada kaca mata watak itu sendiri. Sudut pandang pertama sebenarnya menuntut pengarang untuk memahami keterbatasan watak utama. Pengarang harus memahami pengetahuannya ke atas watak utama tidak semestinya terzahir sama dalam watak utama yang ditulisnya.
Mengimbau sesuatu peristiwa lalu diceritakan dengan rinci dan setepatnya bukanlah suatu ciri-ciri utama naratif yang diceritakan melalui sudut pandang pertama. Tambahan pula watak utamanya, Mira, dilanda depresi pascapartum yang menuntut kepincangan sudut pandangnya pada realiti. Dia harus bergelut demi merentasi kepalsuan halusinasi dan menceritakan realiti kebenaran yang disaksikannya.
Berbalik pada sisi pandang cerpen ini ditulis, saya menyimpulkan naratif ini kononnya diceritakan watak utama sesudah dia melalui fasa depresi pascapartum, diiringi kekuatan memori yang begitu menakjubkan kerana mampu menceritakan dengan rinci detik demi detik dan juga deskripsi perasaan dan emosi yang dilaluinya sepanjang fasa depresi itu.
“Ah, berkesan sungguh ekspresinya.” Aku masih menganggap itu satu kepalsuan wajah untuk membujukku.
Merujuk pada ayat di atas, ia bercanggahan pula dengan tanggapan bahawa naratif ini ditulis setelah watak utamanya menemukan kebenaran dalam peristiwa yang dilaluinya. Sikap prejudis ke atas ibu mertua yang diungkap dalam cerpen ini menampakkan kekeliruan itu masih ada dalam watak utama ketika naratif ini dikarang.
Di sinilah kepincangan cerpen ini dikesan.
Pengetahuan watak utama harusnya terbatas demi menghadirkan efek depresi pascapartum yang berpanjangan dan kekal merencatkan ingatannya. Oleh hal yang demikian, adalah lebih selamat jika pengarang mengungkapkan penceritaan sebegini dalam bentuk sudut pandang ketiga. Pengarang boleh juga menggunakan ungkapan objek dan latar tempat cerita demi menggambarkan “kebiruan” hari sepi sepertimana judul cerpen yang memacu hala tuju cerpen ini.
Risiko menggunakan sudut pandang pertama untuk menggambarkan depresi pascapartum mengingatkan saya pada tulisan William Styron dalam bukunya yang berjudul Darkness Visible. Ia sebuah memoir mengenai depresi seorang pengarang. Pengalaman benar yang merencanakan gelojak perasaan yang dihadapi, kemelut fikiran yang membelenggui dan juga ubat-ubatan yang harus ditelan menurut preskripsi.
Saya percaya, pemilihan subjek yang harus diperkatakan dari sisi seorang wanita yang melalui depresi pascapartum harus diperhalusi lagi. Barangkali, pengarang akan dapat memancing kesayuan dalam cerpennya dengan menelaah bahan bacaan ataupun bertanyakan sendiri pada mantan pesakit depresi pascapartum secara rinci akan apakah perasaan dan kemelut yang dilaluinya.
Menggambarkan kesedihan seorang wanita mendepani tragedi dilukiskan dengan baik dalam cerpen pemenang Hadiah Cerpen Komanwel 2019 berjudul “Death Customs” hasil nukilan Constantia Soteriu. Dalam cerpen ini, pengarang memilih untuk menggambarkan “kebiruan” hari sepi akibat kematian dengan ilustrasi-ilustrasi perbuatan masyarakat yang didepaninya saban hari setelah mendepani kematian orang tersayang. Kekuatan “Death Customs” adalah kemampuan pengarangnya melukis landskap memilukan dengan kata-kata – suatu tahap kepengarangan yang sukar dicapai mutakhir ini. Pemilihan kata yang tepat dan juga pelukisan landskap menuntut pengarang untuk melihat cerpennya dari sudut keseluruhan supaya ia membawa makna judul cerpen yang dikehendaki. Dan sesudah itu, penelitian ke atas setiap hal-hal mikro yang membentuk keseluruhan makna sesebuah cerpen pula dilakukan supaya tiada elemen-elemen yang bercanggahan dengan konteks asal cerpen ditulis.
“Terbayang hari sepiku lalu berwajah biru dalam kepompong depresi yang terencana buatku.”
Sehingga ke akhir ayat dalam cerpen ini ditulis, saya tidak menemukan “kebiruan” yang betul-betul mengesankan. Ayat terakhir dalam cerpen ini ibarat suatu tempelan demi menyedapkan penamat tetapi tidak berhasil mendukung keseluruhan makna dalam cerpen ini. Menggunakan perkataan “terbayang” itu sendiri seolah-olah menggambarkan ketika naratif ini ditulis, watak utamanya masih bergelut dengan depresi pascapartum. Ia bercanggahan pula kemampuan watak utamanya mengenalpasti kebenaran dan kepalsuan dalam kata-kata setiap watak yang didepaninya.
Menyebut perihal tempelan, suka untuk saya mengingatkan agar kepuitisan sesebuah naratif harus melihat juga pada kesesuaian keadaan. Memandangkan cerpen ini kononnya dinaratifkan oleh seorang pesakit depresi pascapartum, ia harus sarat makna dengan kata-kata yang tepat tanpa perlambangan yang sebegitu banyak demi mengelakkan kesedihan yang diungkapkan tampak superfisial.
Kita tidak mengenakan mekap atau bedak demi kelihatan cantik tika terlantar di katil sakit sambil membuat video yang ditonton oleh ribuan manusia di media sosial. Begitu jugalah sifat sebuah naratif – ia harus sesuai dengan konteks demi menggambarkan matlamat sesebuah cerpen itu ditulis.
Oleh itu, saya mencadangkan pengarang agar menelusuri setiap makna perkataan dalam setiap olahan perumpamaan yang diselitkan demi memastikan ketepatannya terjaga. Puitis tidak semestinya harus dalam menukilkan sebuah fiksyen – ia harus tepat dengan konteks.
Di samping itu juga, sikap berhati-hati ketika menulis dari sudut pandang pertama amat penting supaya pengarang tidak terlanjur menyuguhkan pembaca dengan informasi yang sepatutnya watak utama tidak ketahui.
Potensi pengarang dalam mengungkapkan permasalahan wanita, khususnya depresi pascapartum harus dipuji. Namun pengarang harus memahami hakikat kesukaran mengarang cerpen sedemikian yang menuntut suatu penggalian mendalam ke nubari individu yang benar-benar melalui pengalaman sedemikian.
Semestinya, pengarang menampakkan gaya penulisan tersendiri yang boleh dipupuk dengan lebih baik seiring dengan kematangan dan juga pembacaan karya-karya yang baik. Diharapnya pengarang akan terus-menerus mengarang demi membentuk kekuatan yang boleh diharapkan dalam cerpen-cerpen yang akan datang.