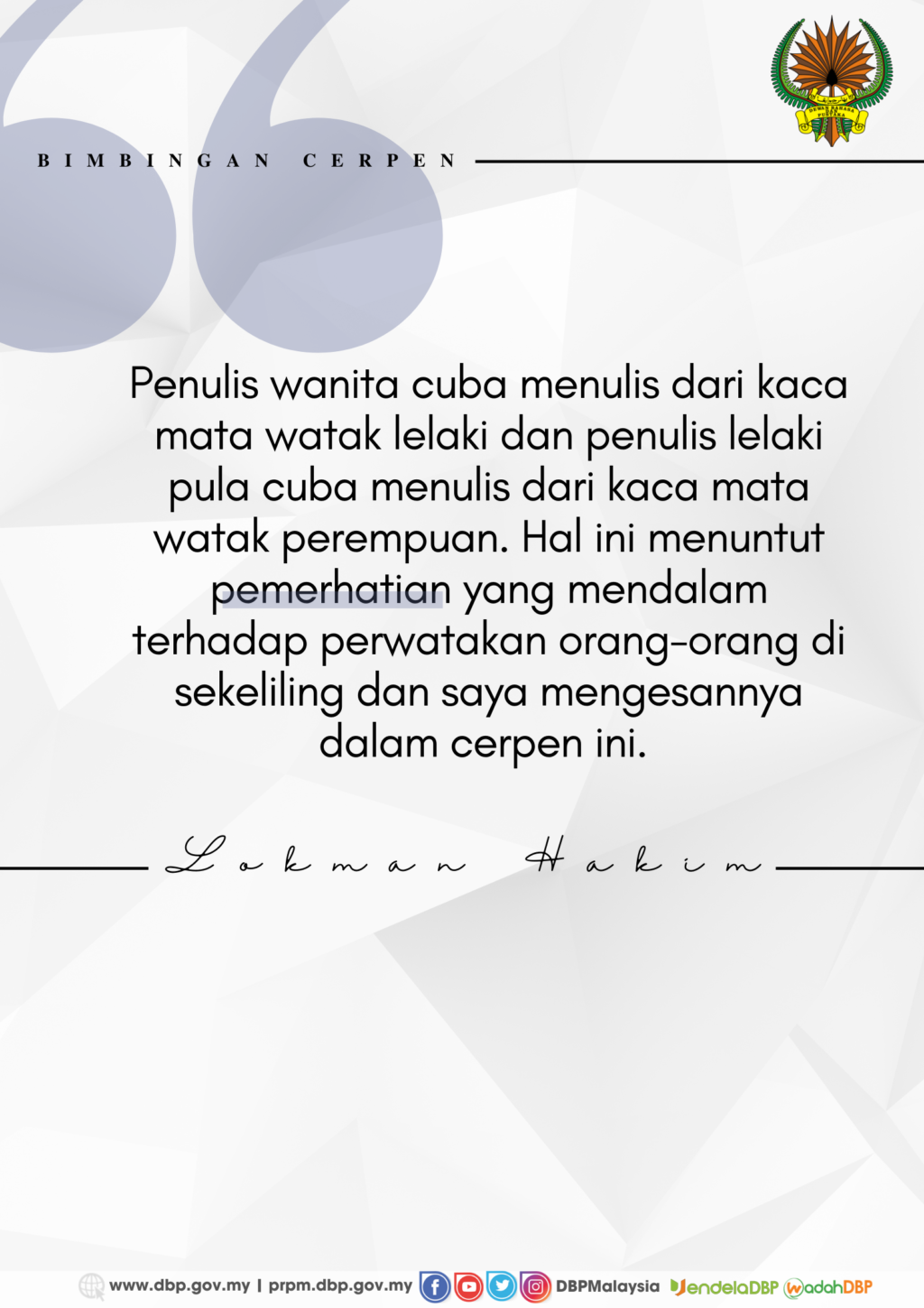

Oleh: Lokman Hakim
MEMBACA “Hajat Puspa Paru” akan membawa pembaca ke dalam ruang lingkup seorang pesakit barah paru-paru yang melihat dunia dari kaca matanya yang begitu peribadi sifatnya. Mutakhir ini, saya mendapati para penulis kita, khususnya yang baru berjinak-jinak dengan dunia penulisan sudah ada keberanian menulis dari kaca mata watak utama yang berbeza jantinanya daripada penulis. Ia harus dipuji tetapi membangkitkan suatu persoalan lain – adakah ia ditulis dengan baik dan tepat?
Penulis wanita cuba menulis dari kaca mata watak lelaki dan penulis lelaki pula cuba menulis dari kaca mata watak perempuan. Hal ini menuntut pemerhatian yang mendalam terhadap perwatakan orang-orang di sekeliling dan saya mengesannya dalam cerpen ini. Paling jelas, hal itu barangkali perlu dialami oleh orang terdekat dengan pesakit yang sedemikian rupa. Awang Alfizan memulakan penulisan dengan pertanyaan sebegini:
“Adakah terasa sakit tatkala sekuntum puspa dipetik dari pohonnya? Sakit yang berdenyut dari pucuk dedaun hingga ke akar tunjang?”
Saya menggemari usaha penulis untuk kekal puitis meskipun menulis sebuah cerpen. Tambahan pula, sebuah cerpen yang bagus sering kali dimulakan dengan ayat pemula yang mengagumkan ataupun sedikit sebanyak membangkitkan rasa ingin tahu pada pembaca. Apabila penulis cuba menyerapkan perkataan-perkataan yang janggal tetapi indah ke dalam sebuah cerpen, ia suatu perkara yang baik. Namun ia harus dilakukan dengan sikap berhati-hati agar tidak bersalahan dengan konteks. Dan paling utama, ia harus bersebati bersama ayat-ayat yang terjalin secara natural. Hal ini menuntut pengalaman pembacaan yang luas dan juga keterbiasaan penulis menggunakan perkataan-perkataan indah tapi janggal. Dalam erti kata lain, penulis harus arif benar dengan maksud perkataan yang digunakan itu sebelum memanfaatkannya dalam penulisan kendiri.
Malangnya, penulis kelihatannya cuba menerapkan perkataan-perkataan janggal demi menggantikan perkataan-perkataan lazim dengan niat untuk menyedapkan karya tetapi sudahnya ia mencacatkan karya.
“Tiba-tiba sahaja spatula yang aku pegang terlepas dari genggamanku.”
Spatula, tidak boleh disinonimkan dengan sudu mahupun garpu dek kerana bentuk dan fungsinya yang sangat berbeza dengan kedua-dua objek tersebut. Namun, keghairahan penulis mahu menampakkan penguasaan perbendaharaan kata yang banyak telah memakan diri.
Mengapa penulis memilih “sekuntum puspa” dan bukannya “sekuntum bunga”? Saya beranggapan ia bukan masalah. Cuma, apabila menggunakan sudut pandang pertama selaku penceritaan, ia akan menggambarkan kecenderungan watak selaku pencerita tersebut. Tidak ramai penulis yang menyedari bahawa apabila menggunakan sudut pandang pertama selaku pencerita utama, ia harus punya karakternya tersendiri. Memetik John Yorke dalam bukunya yang berjudul Into the Woods:
“Kita semua serupa – namun kita juga berbeza. Setiap orang sedikit sebanyak berkongsi garapan asas psikologi di mana kita semua memiliki kemampuan untuk mencintai, berasa cemburu, beranak-pinak, bersifat defensif, bersikap terbuka, berdendam dan juga berbuat baik. Kita semua memiliki pengalaman ataupun pengetahuan mengenai kebapaan, keibuan, kanak-kanak dan juga cinta lalu kita menampakkan ciri-ciri dan juga pengaruh ini dalam kadar yang berbeza bergantung pada siapa dan apakah diri kita. Sepertimana peribahasa “Rambut sama hitam, hati lain-lain,” begitulah juga dengan garapan psikologi kita.”
Perkara yang sering terjadi ialah penulis secara tidak sengaja meletakkan dirinya sendiri dalam karakter tersebut. Dalam erti kata lain, dalam watak utama ini, iaitu seorang pesakit kanser yang juga wanita berusia ini, masih kelihatan seorang Awang Alfizan cuba menyembunyikan jejak-jejaknya tetapi tidak berhasil.
Ayuh, kita cerakinkan watak utama ini melalui penceritaan yang digarap penulisnya. Puspa, seorang wanita berusia yang menghidap kanser paru-paru yang merebak ke otaknya. Penceritaan ini ditulis melalui kaca matanya, sebelum dan ketika dia menghadap kematian. Maka, ini adalah cerpen yang ditulis dari kaca mata seseorang yang sudah meninggal dunia. Di sinilah elemen superfisial dikesan. Penulis cuba menerapkan sebuah duka mendalam pesakit kanser yang merebak bukan sahaja pada diri pesakit tetapi juga kepada ahli-ahli keluarganya sehingga terlupa perihal konsep penyampaian sebuah cerita.
Sebuah naratif disampaikan kepada pembaca dalam keadaan tenang, lazimnya. Seorang ayah atau ibu membacakan cerita kepada anak-anak sebelum mereka tidur. Kita mendengar cerita di kedai kopi dalam keadaan santai. Oleh yang demikian, melihat dari perspektif sebegini, maka di manakah penceritaan Puspa, watak utama cerita ini, dilakukan? Selaku pembaca, kita ibarat didatangi ‘roh’ Puspa yang menceritakan bagaimana dia mendepani kematiannya dengan perincian yang mengharukan. Kegagalan penulis melihat dari perspektif ini membuatkan cerpennya dirasakan sedikit superfisial tetapi ia masih terkawal. Terdapat keseimbangan dalam penceritaan yang begitu melankolik sekali gus menenggelamkan isu persepsi yang aneh ini.
Markus Zusak menggunakan narator dewa maut demi mengungkapkan perihal watak utama, Liesel dalam fiksyen sejarahnya yang berjudul The Book Thief. Penulis ini tidak pernah culas mengingatkan pembaca sepanjang penceritaannya bahawa dia ialah dewa maut yang mampu meneliti kehidupan seorang manusia dari kecil hingga ke hujung usia tanpa sebarang kepayahan lantas menceritakannya dengan begitu rinci.
Tidak dinafi, jika ditelaah cerpen ini pada permukaan, tidak sukar untuk kita hanyut dengan lenggok bahasa yang puitis dan berjaya membawa mood sedih sepanjang penceritaannya. Kebolehan memperincikan hal-hal mikro dalam suatu babak demi babak sekali gus mengasingkan hal-hal banal merupakan suatu teknik yang harus dipuji. Oleh itu, saya akui, penulis punya potensi menggarap karya yang sarat emosi pada masa akan datang tanpa sebarang masalah.
Cabaran untuk menghasilkan sebuah cerita dari sisi pandangan watak yang jelas sekali berbeza personaliti, usia, jantina dan perwatakannya berbanding penulis sedaya upaya diatasi dalam cerpen ini. Oleh yang demikian, terlihatlah beberapa kepincangan yang barangkali boleh diperbaiki dalam karya-karya seterusnya.
“Sebenarnya, boleh sahaja anak-anakku mengupah pengasuh luar untuk merawat anak mereka.”
Barangkali, penulis memaksudkan perkataan “menjaga” apabila meletakkan perkataan “merawat” dalam ayat di atas. Kesilapan sebegini menjelaskan serba sedikit mentaliti penulis yang punya kecenderungan menggunakan perkataan-perkataan janggal demi menggantikan perkataan-perkataan yang lazim digunakan.
“Pada hari itu, aku memerhati seorang nenek yang seusiaku sedang beratur mengambil ubat bersama cucunya di kaunter farmasi.”
Di sinilah cabaran menulis sebuah watak yang langsung berlainan daripada penulis. Kita tidak melihat orang seusia kita dengan kaca mata usia. Seorang remaja tidak memanggil rakan seusianya “remaja”. Seorang lelaki pertengahan usia yang melihat rakan sebayanya tidak akan memanggil rakannya itu “pak cik”. Meskipun hal ini terpakai untuk kanak-kanak, yang tidak keberatan memanggil rakan sebayanya “budak”, tetap janggal untuk seorang wanita berusia memanggil wanita berusia yang lain sebagai “nenek”. Melainkan wanita berusia itu percaya orang yang dilihatnya itu terlalu tua untuk dianggap sebaya dengannya. Namun, jelas tertera penulis menulis begini: “Seorang nenek yang seusiaku.”
Ayat itu menampakkan pergelutan penulis dalam mendepani kekeliruan sepanjang penciptaan karya ini. Penulis mengerti bahawa dia harus menulis dari kaca mata seorang wanita berusia yang mendepani maut, tetapi dalam waktu yang sama, dia juga terikat dengan kaca matanya sendiri yang melihat wanita tua itu selaku nenek. Penulis ingin memisahkan peribadinya sendiri daripada watak utama yang diciptanya, tetapi jelas, ia usaha yang agak sukar dilakukan.
“Usai aku menghabiskan kata-kata terakhirku, nafasku mula tercungap-cungap. Dadaku berombak. Bebola mataku memandang ke atas.”
Saya tidak tahu bagaimana perasaannya ‘mati’. Bahkan saya juga tidak pernah melalui pengalaman hidup-mati, maka saya tidak berani memperkatakan ayat di atas itu tepat atau tidak. Namun, ayat tersebut kelihatan janggal kerana ia menjelaskan keadaan yang sedang berlaku pada watak utama dari sudut pandangan orang ketiga. Pemilihan penerangan yang digunakan bukanlah sesuatu yang ditutur oleh orang yang mengalaminya. Barangkali, ia akan jadi lebih baik sekiranya ia ditulis begini:
“Usai aku menghabiskan kata-kata terakhirku, nafasku serasa berat. Dadaku serasa sesak, bagai ditelan badai lautan. Bebola mataku dirasakan seolah-olah tidak lagi berada di tempatnya.”
Ya, apa yang saya cuba ungkapkan di sini ialah, penulis seharusnya menggunakan pandangan peribadi watak itu sendiri, yakni apa yang dia alami dan rasai. Menerangkan keadaan yang dilalui watak utama sepertimana yang kita lazim lihat pada orang yang mendepani sakaratulmaut menampakkan penulis terperangkap dalam baur penceritaan antara dirinya selaku penulis dengan dirinya selaku watak Puspa. Memetik kembali John Yorke, beliau ada memperkatakan: “Konflik di antara bagaimana kita mahu ditanggapi dan apa yang sebenarnya kita rasai itu adalah akar untuk semua jenis perwatakan.”
Oleh itu, sebagai apakah Puspa mahu dirinya ditanggapi pembaca dan apakah yang dia sebenarnya rasai? Melalui pembacaan cerpen ini, kita tahu apa yang dia rasai. Kesakitannya, kesedihannya dan juga kegembiraannya dijelaskan melalui interaksinya dengan watak-watak lain. Bahkan dalam penceritaan perihal yang berlaku ke atasnya sehingga ia berakhir dengan kematian, Puspa menceritakan ehwal keluarganya, bilangan ahli keluarga dan cucu-cucunya. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, cerpen ini serasa janggal kerana ia ditulis oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Kini ia jadi lebih janggal kerana kita tidak jelas, apakah yang Puspa inginkan daripada pembaca yang meneliti kisah ringkasnya dalam cerpen ini?
Baiklah, kita kembali semula pada John Yorke. Dia juga ada memperkatakan:
“Terdapat fakta ringkas yang mengatakan baik dalam fiksyen mahupun dalam diri kita sendiri (seandainya kita jujur pada diri sendiri) terdapat percanggahan yang memisahkan.”
Dalam cerpen ini, Puspa yang sudah meninggal dunia ini ingin menceritakan perihal kematiannya, iaitu suatu rantaian babak demi babak yang menyedihkan. Kita dibawa mengharungi kesakitannya menghadapi barah, menghadapi kesedihan ahli keluarganya dengan berita penyakitnya itu dan juga pada waktu yang sama, kita disajikan dengan kemanisan ikatan kekeluargaan yang utuh dan makna penerimaan takdir sebulatnya.
Oleh yang demikian, watak Puspa ini sebenarnya lengkap secara manusiawinya. Ia punya percanggahan dalam diri. Ia tidak sempurna dan tidak mampu mengatasi kematian. Bahkan dia menerima kematian dengan reda setelah diulit rasa kasih sayang yang mendalam daripada ahli-ahli keluarganya.
Kekeliruan dan campur baur watak utama dengan suara penulis yang sesekali masuk ke dalam cerpen menampakkan kekurangan pengalaman penulis dalam penghasilan karya sebegini rupa. Ia juga menampakkan suatu lagi kemungkinan, iaitu karya ini digarap berdasarkan pemerhatian ke atas peristiwa kematian seseorang yang dekat dengan penulis. Terdapat suatu garis kabur persempadanan antara watak yang digarap berdasarkan imaginasi total berbanding watak yang digarap berdasarkan individu sedia ada.
Apa-apapun, usaha penulis menulis sebuah cerpen yang diterajui watak yang jelas sekali berbeza dengan fizikal dan psikologi penulis, harus dipuji. Saya percaya, jika penulis konsisten menggarap cerpen demi cerpen dan juga berusaha untuk menulis dengan lebih baik, ia akan membawa kita, selaku pembaca, ke ruang kemungkinan yang tidak terjangka.
Bolehlah disimpulkan bahawa penulis punya usaha untuk menulis dengan baik. Dengan pembacaan bahan bacaan yang baik dan bermutu, disusuli penyerapan elemen pemikiran dalam karya-karya yang sarat emosi sebegini, penulis akan berjaya menghasilkan karya penuh impak di masa akan datang.