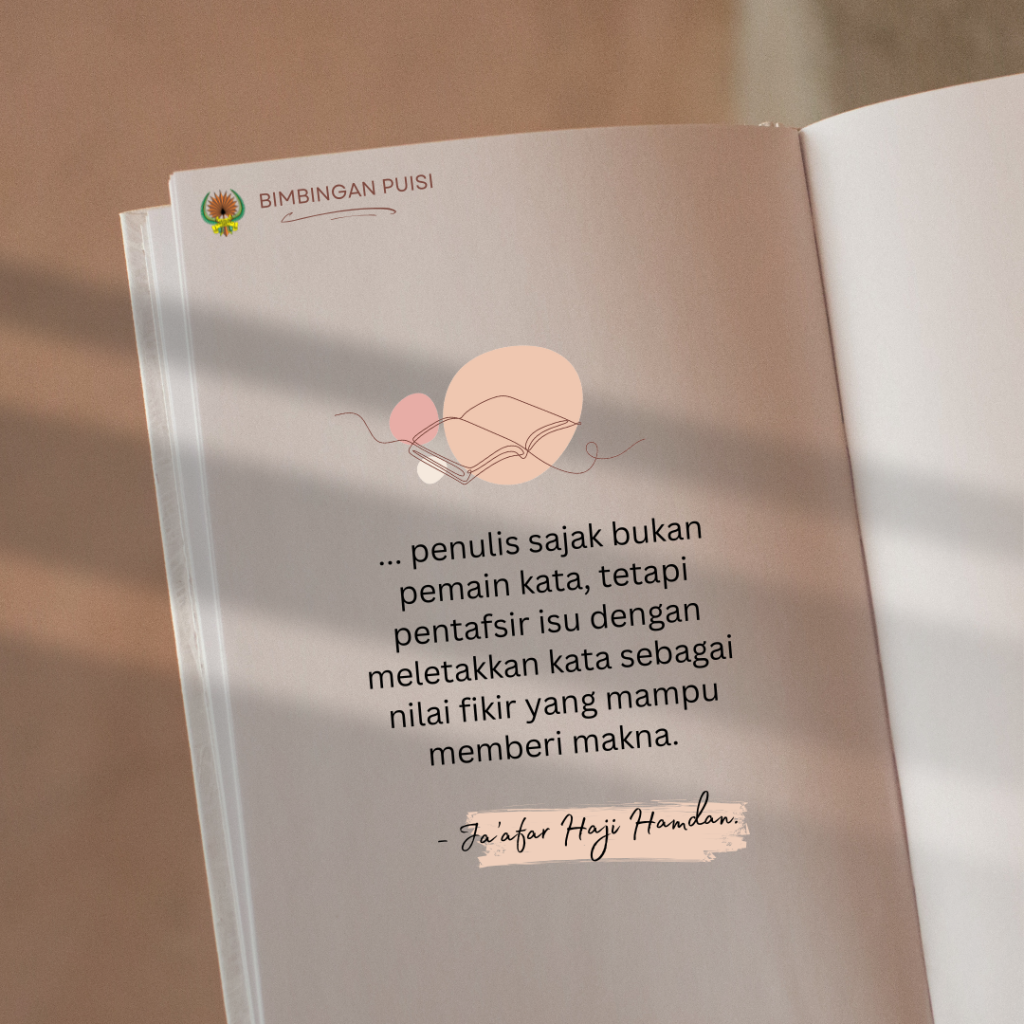

APABILA membaca sesebuah karya sastera, pemikiran dan estetika menjadi pilihan. Pemikiran membawa gagasan dan estetika memberi keindahan. Keseimbangan antara dua faktor berkenaan saling melengkapi. Andai sesebuah karya melebihi aspek pemikiran dan meminggirkan aspek estetika, maka karya tersebut kaku dan tidak bermaya. Sebaliknya, melebihkan aspek estetika tanpa mengutarakan nilai pemikiran menyebabkan karya yang terhasil kosong dengan pemaknaan.
Perkara ini tidak terkecuali dalam penghasilan sajak. Walaupun ramai yang beranggapan sajak hanya memerlukan kata-kata sebagai wahana karyanya, namun, pada kata-kata itulah tersirat pemikiran sekali gus estetikanya. Oleh itu, tanggapan bahawa sajak merupakan genre sastera yang mudah dihasilkan sebenarnya tanggapan yang mengarut serta melulu.
Mungkin ramai yang boleh menghasilkan sajak tetapi tidak ramai yang mampu mencipta sajak. Hal ini terbukti apabila seseorang mampu menulis sajak dengan mengulangi ungkapan sajak yang mungkin pernah dibaca atau terpengaruh serta teringat lirik lagu yang syahdu dan puitis yang sering didengarnya. Pengulangan ini terkadang terjadi tanpa sedar kerana rasa nikmat pada pemaknaan kata-kata dalam ungkapan tersebut.
Seseorang yang mencipta sajak sering terperangkap dalam penentuan kata yang dipilih untuk merasionalkan cakupan makna itu sesuai dan padan dengan setiap gagasan yang hendak diketengahkannya. Pencarian kata untuk menterjemahkan episod cerita melalui satu perkataan memungkinkan penghasilan gaya bahasa sama ada metafora, personifikasi atau sebagainya bagi memaparkan cerita pemikiranny
Gandingan dua atau tiga perkataan menjadi ungkapan sebagai episod cerita inilah yang menyerlahkan estetika sesebuah sajak. Kemampuan membina ungkapan penuh pemikiran dalam salutan estetika menjadi amat sukar apabila penulis sajak itu sendiri tidak mengetahui fokus cerita dalam sajaknya. Apakah menulis kerana ingin menyatakan sesuatu pada pandangan diri yang kabur? Atau menulis sajak hanya kerana ingin menggayakan bahasa yang menarik?
Oleh itu, kata tunggal atau tersendiri atau yang digabungkan untuk membina episod cerita dalam sajak terlalu sukar menjelmakan hasrat pemaknaan. Natijahnya, ada penulis yang mengungkapkan secara gambaran dengan meleret-leretkan kata-kata sebagai alun atau alir cerita.
Walhal, gaya drastik dan teknik melulu ini meminggirkan estetika secara tidak langsung kerana ditenggelamkan oleh kelewahan atau unsur bombastik yang keterlaluan melalui pemakaian bahasa yang berjela-jela atau tidak tepat.
Hakikatnya, penulis sajak bukan pemain kata, tetapi pentafsir isu dengan meletakkan kata sebagai nilai fikir yang mampu memberi makna. Tugas penulis sajak perlu mengutamakan “keranuman” kata untuk disajikan dalam ungkapan sesebuah sajak. Sajian yang dihidangkan pada pembaca sudah tentu perlu sedap bukan sahaja pada mata yang memandang, tetapi juga pada rasanya.
Sajak yang terlalu memberi tumpuan pada permainan kata tanpa memberi makna hanya akan menjadi sebuah sajak yang bercerita dengan bungkusan kata-kata yang mengkhayalkan. Seperti makanan sedap tetapi mempunyai kesan sampingan yang boleh membawa penyakit kerana kandungan gula atau lemaknya yang tinggi, tetapi tidak mempunyai khasiat yang perlu untuk kesihatan.
Untuk memudahkan perbincangan kita tentang pemikiran estetika dalam sajak, mari kita sama-sama meneliti tiga buah sajak yang telah tersiar dalam ruangan ini pada minggu lepas, iaitu” Tidur Yang Masih Bangun” nukilan Rayner RK, “Pinjam” nukilan Salleh Muslim dan “Jala Tua” nukilan Qurratu Aini Izzatie.
Sajak pertama berjudul “Tidur Yang Masih Bangun” merupakan sajak yang mengekspresikan suasana secara paradoks. Walaupun janggal pada pengungkapan tetapi memaknakan suasana secara tersirat dan mampu mencetuskan sisi penilaian kita sebagai manusia dalam memahami kehidupan. Secara alamiahnya, tidur merupakan situasi rehat.
Namun dalam sajak ini, tidur menjadi wacana perhitungan untuk mencari kehidupan itu sendiri. Perhatikan keseluruhan sajak ini;
Dalam lena yang separuh mimpi,
aku mendengar derap waktu berlalu,
desir tayar di lorong sempit,
lalu-lalang manusia yang tak pernah berhenti.
Di kota ini, malam tak mengenal diam,
neon berkedip, sibuk berbisik,
menyulut resah dalam kantung mata,
membakar damai dalam detik yang singkat.
Aku ingin tidur yang sebenar tidur,
bukan terjaga dalam lena palsu,
bukan mimpi yang dihujani dering,
bukan nyenyak yang tercarik bayang.
Aku rindu bunyi angin di celah daun,
bukan gemuruh mesin menelan sunyi,
aku ingin gelap yang mendakap,
bukan kelam yang menjebak sepi.
Tuhan, di mana lena yang damai?
di mana pagi yang tidak tergesa?
di mana manusia tidak mengejar,
tetapi berjalan bersama waktu yang rela?
Aku masih bangun dalam tidur ini,
mengharap malam mengerti rintih,
andai ada ruang untuk terlelap,
biarlah ia dalam pelukan yang benar-benar hening.
Dalam rangkap pertama sajak ini, kecelaruan situasi dibayangi oleh “desir tayar” dan “lalu-lalang manusia” sebagai gangguan “lena yang separuh mimpi”. Paradoksnya “mendengar derap waktu berlalu” suatu imaginasi pemikiran yang di luar konteks. Pertembungan dua situasi secara nyata dan imaginasi ini membuka makna dalam takrif penceritaannya sebagai pemula pemikiran estetikanya.
Ini dapat dihayati pada rangkap kedua, apabila paradoks itu dimatikan dengan ungkapan “malam tak pernah diam” kerana “neon” berbisik tetapi “menyulut resah” yang boleh dianggap ungkapan segar dan sesuai merentasi “kantung mata”. Hanya kesan “menyulut” hingga mampu “membakar damai” agak drastik tetapi masih memaknakan kesan ceritanya.
Kesan ini hilang fokus apabila pada rangkap ketiga terserlah fenomena “tidur yang sebenar tidur” dipersoalkan dengan “lena palsu”, “mimpi dihujani dering” dan “tercarik bayang”. Penggunaan personifikasi atau metafora yang menerjah nilai makna yang agak keterlaluan akan menjadi terlalu melulu sehingga merencatkan estetika ungkapannya. Sebagai contoh, persoalan “tidur” dengan “mimpi” pada “hujan” sebagai “dering” secara lateralnya, menyamankan tidur, bukan suatu pertentangan yang objektif terhadap kesan gangguan pada tidur.
Ini juga terkesan dalam rangkap keempat apabila “rindu bunyi angin” pada “celah daun” dibandingkan dengan “gemuruh mesin”. Perbandingan ini telah menolak pemikiran estetika secara langsung kerana secara rasionalnya, dua konteks berkenaan bukan suatu yang wajar dikaitkan sebagai penentuan makna mencari kesan “rindu” yang mewajarkan situasi nikmat sebuah tidur. Bahkan permintaan “ingin gelap yang mendakap” untuk menolak “kelam yang menjebak sepi” juga terlalu drastik sebagai pertembungan pemikiran estetikanya.
Kesegaran ungkapan pada rangkap awal terutamanya dalam sisi estetika seakan-akan lenyap pada rangkap yang kelima. Jelas, pertanyaan dalam rangkap kelima ini menjadi amat langsung walaupun cuba dimaniskan dengan ungkapan puitis. “Lena” pada baris pertama dan “pagi” pada baris kedua, bukan dijadikan persoalan tetapi seharusnya dijadikan kronologi pemikiran estetika untuk membina “manusia” untuk “mengejar” dan bukan “berjalan”. Perkara ini penting difahami kerana “waktu” bukan situasi “rela” tetapi suatu ketetapan dan kemestian berlaku tanpa makna tunggu dan nanti.
Pada rangkap keenam, jelas sajak ini tidak dapat menyimpulkan apakah sebenarnya gagasan yang cuba hendak dikongsi kepada pembaca selain hanya menimbulkan persoalan untuk dilalui tanpa dihayati arah tuju pemikiran estetikanya. Sajak ini baik pada estetikanya, tetapi kurang makna pada pemikirannya. Kalau ditambah baik dengan menelusuri idea utama, iaitu “mencari tidur yang damai”, pasti sajak ini boleh mewacanakan “kehidupan” sebenarnya “sebuah tidur yang dipinjamkan”.
Sajak kedua yang akan kita bincangkan berjudul “Pinjam”. Sajak ini merupakan sajak yang agak peribadi. Penggunaan watak “aku” dalam ungkapan sajaknya membawa makna rentetan peristiwa yang dilaluinya.
Sajak sebegini kalau mahu diperkatakan melalui sisi pemikiran estetika, memerlukan ketekunan memilih kata yang membawa gagasan ungkapan pesona, iaitu ungkapan yang mengajak kita mencari pemaknaannya. Perhatikan keseluruhan sajak ini;
Pinjamkan hatimu
pinjamkanlah seketika
untukku berteduh
selagi hujan masih lebat
agarku masih kuat
Bukakan hatimu
bukakanlah perlahan
agar sinarmu tak berlebihan
untuk kau harungi jalan berliku
merempuh belantara
menuju senja
Pejamkan matamu
pinjamkanlah lenaku
tatkala senja berlabuh
Malam bersauh
kerana sinarmu
hanyalah pinjaman
Apabila memperkatakan tentang pemikiran, perkara utama yang diteliti ialah idea. Oleh itu, apabila kita menekuni rangkap pertama sajak ini, jelas kata “pinjamkan hatimu” untuk “berteduh” seakan-akan tidak menampakkan estetika sama ada pada pemikiran atau pemaknaannya.
Walaupun dijelmakan situasi “selagi hujan masih lebat” sebagai perisai rasa “masih kuat”, pengungkapan sedemikian hanya luahan yang langsung dan tidak memberi apa-apa kesan dalam sifat sajaknya.
Kemudian, pada rangkap kedua, permintaan “bukakan hatimu” dengan ungkapan “sinarmu tak berlebihan” yang dikaitkan dengan “merempuh belantara” jelas menampakkan kekeliruan dalam penggunaan gaya bahasa. Kekeliruan ini secara tidak langsung membina kecelaruan imej pada tiga kata objektif, iaitu “hati”, “sinar” dan “belantara”.
Apabila kecelaruan imej berlaku tanpa kesejajaran episod cerita, paling ketara berlaku penyimpangan pemikiran dalam mencari pemaknaan dalam sesebuah sajak. Ini jelas pada rangkap kedua yang menimbulkan persoalan, apakah yang sebenarnya hendak diceritakan oleh penulis? Pertanyaan ini bukan elemen estetika tetapi ketidakmampuan penulis menunjangi estetika itu sebagai unsur tersirat.
Kesan ini terus berlanjutan pada rangkap ketiga apabila kaitan “pejamkan matamu” dengan “pinjamkanlah lenaku” hanya sorotan sebuah ungkapan yang kosong tanpa membawa makna walaupun “senja” boleh kita bayangkan sebagai garis penghujung. Tetapi di manakah penghujung itu perlu dihalakan? Bahkan, pada rangkap terakhir, semakin jauh pemaknaannya apabila ungkapan “hanyalah pinjaman” sebagai penutup episod cerita. Apakah wajar sajak ini dikategorikan sajak bertemakan agama? Saya tinggalkan pertanyaan ini untuk penulisnya.
Sajak ketiga yang akan kita bincangkan berjudul “Jala Tua”. Sajak ini boleh dikatakan sebagai sajak bertemakan kemanusiaan yang mempersoalkan tentang kehidupan. Penanda wacana pada kata “jala” sebagai penentu rezeki dikaitkan dengan kata “tua” jelas membawa kesan kelamaan terhadap proses kehidupan itu sendiri. Apa yang menarik tentang sajak ini ialah kependekan sajak untuk bercerita tentang isu yang besar.
Perhatikan keseluruhan sajak ini untuk memudahkan perbincangan kita;
Di hulu sana
kulihat seorang lelaki
terbongkok-bongkok menarik jala
seraya mendengus melepas beban
derita pada Batang Cinta
Bermudik mengheret jala tua
menembus hampa hidup
nafas tuanya
menemani perjalanan tanpa kata
Jala tua penuh luka yang dibalut duka
mungkin esok tak lagi mencium matahari
Perwatakan “seorang lelaki” pada rangkap pertama dilukiskan melalui ungkapan “terbongkok-bongkok”. Pelukisan watak sebegini dalam sajak dalam konteks pemikiran estetika memerlukan kehalusan makna pada kata yang digunakan. Kata “bongkok” untuk menggambarkan seorang tua sudah agak klise dan tidak sesuai sebagai kata ungkap dalam sajak. Bahkan, kata itu sudah “membunuh” pembacaan seterusnya.
Kehalusan ungkapan seperti “hampa” sepatutnya lebih banyak dibina dan dijadikan gaya bahasa apabila menghasilkan sajak sebegini. Bayangkan ungkapan pada rangkap kedua dibina sebegini;
Bermudik mengheret jala tua
dengan nafas hampa
telah menemani perjalanannya
tanpa ada lagi kata-kata
Sajak “Jala Tua” ini sebenarnya belum cukup “masak” untuk dihidangkan kepada pembaca. Oleh itu, setiap ungkapannya menjadi agak tawar dan kurang menyelerakan. Ini berbeza dengan ungkapannya dalam rangkap yang ketiga apabila penegasan ungkapan “luka yang dibalut duka” jelas memberi pemikiran estetikanya walaupun agak drastik. Cuba bayangkan sajak ini diubah suai sebegini;
Jala tua penuh luka dibalut duka
mungkin esok tidak lagi mencium matahari
Kerana di hulu sana
seorang lelaki masih setia
seraya mendengus menarik jala rasa
dengan melepaskan beban derita
pada Batang Cinta
Esok
mudiknya mengheret jala tua
dengan nafas hampa
yang telah menemani perjalanannya
tanpa ada lagi kata-kata
Bagaimanapun, ini sekadar cadangan untuk mewajarkan pemikiran estetika pada sajak ini lebih rasional dan munasabah dibina. Penggunaan rangkap sebagai pemula cerita cukup penting sebagai pancingan bacaan dan penelitian mencari pemaknaan dalam cerita sajak. Oleh itu, sajak bukan sewenang-wenangnya perlu dihasilkan secara kronologi tetapi perlu juga secara piramid terbalik, iaitu mendahulukan yang menimbulkan persoalan dan diakhiri dengan penegasan.
Tahniah kepada ketiga-tiga penulis sajak yang dibincangkan kerana sudah mempunyai daya usaha serta idea mencetuskan persoalan dalam sajak. Terus tingkatkan pembacaan. Carikan kelainan konteks penceritaan dengan meneroka sisi-sisi yang boleh menggugah pemikiran estetika sama ada dalam persoalan isu, gaya bahasa atau teknik penulisan.
Oleh Ja’afar Haji Hamdan